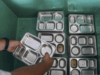Setiap manusia dipandang sebagai perwujudan khusus atau “diferensiasi” alam, yang harus menyatukan diri dengan aturan alam yang agung itu, dan hak-haknya muncul dari fungsi dan tugas sosial masing-masing. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, perkembangan manusia, budaya dan bangsa harus berlaku menurut asas “tri-kon” (kontinu, konvergen, konsentris): “kontinu” dengan alamnya sendiri, “konvergen” dengan alam di luarnya, untuk menuju ke arah persatuan “konsentris” yang universal, yaitu bersatu dengan alam besar, namun tetap memiliki “kepribadian” sendiri (Reeve, 20013: 17).
Meski terdapat titik temu, kedua arus kebudayaan memperlihatkan perbedaan perspektif dalam mengaktualisasikan semangat kekeluargaan itu. Sifat pedalaman yang konsentris lebih memberikan tekanan pada pentingnya merawat persatuan-kesatuan (unity). Sedangkan sifat pesisir yang dispersal lebih memberikan tekanan pada pentingnya merawat perbedaan-keragaman (diversity). Secara garis besar, Soekarno mewakili perspektif yang pertama, sedangkan Mohammad Hatta mewakili perspektif yang kedua.
Dalam menekankan unitas, Bung Karno lebih memilih bentuk negara kesatuan, mengedepankan kewajiban warga di atas hak, menghendaki penyederhanaan partai bahkan mengidealisasikan adanya satu partai pelopor (PNI-Staatspartij), dan perlunya pembentukan kolektivisme golongan fungsional (corporate state) sebagai akutalisasi semangat kekeluargaan dalam mengatasi partikularitas partai politik, serta mengutamakan kepemimpinan yang kuat.
Dalam menekankan diversitas, Bung Hatta lebih memilih bentuk negara federal, lebih memperhatikan hak warga, mendukung pembentukan multi-partai, memilih demokrasi parlementer, dan pentingnya mengembangkan individualitas (bukan individualisme) untuk mengimbangi kemungkinan kolektivisme terbajak oleh kekangan tradisi (feodalisme), serta tidak mengutamakan kepemimpinan yang kuat.
Pergulatan antara kedua pendekatan itu memperoleh sintesisnya dalam nilai dasar Pancasila, yakni semangat gotong-royong. Adapun substansi dari semangat gotong royong itu tiada lain adalah apa yang disebut oleh Profesor Nicolaus Driyarkara sebagai “ada-bersama-dengan cinta” (liebendes Mit-sein); bahwa cinta kasih sebagai pemersatu sila-sila. Dengan semangat gotong-royong itu, Konstitusi Proklamasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) disusun dalam sistematik negara kekeluargaan.
Dalam semangat gotong-royong dan sistematik negara kekeluargaan, bentuk negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercaya bisa menjamin persatuan yang kuat bagi negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (unitary). Meski demikian, mereka sepakat bahwa untuk mengelola negara sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa tersentraliasi dengan mengandalkan inisiatif segelintir elit di Jakarta. Negara Indonesia sepatutnya dikelola dengan mengadopsi unsur pendekatan federal dengan melibatkan peran serta daerah lewat desentralisasi dan dekonsentrasi. Termasuk perlunya pembentukan pemerintahan daerah berdasar atas permusyawaratan dengan menghormati “hak-hak asal-usul” dari daerah yang bersifat istimewa, seperti daerah kerajaan (Kooti) dan daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa.
Kewajiban warga tetap dikedepankan, seraya menjunjung tinggi hak-hak dasarnya, agar negara kekeluargaan tidak menjelma menjadi negara kekuasaan. Soepomo sebagai representasi arus “pedalaman” yang bertindak sebagai Ketua Tim Kecil Perumus Rancangan UUD bersedia menempuh pilihan kompromistis, dengan menambahkan pasal “yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain yang diatur oleh undang-undang”.
Dengan pasal tersebut, warga bebas mendirikan partai politik, namun tetap diletakkan dalam kerangka negara kekeluargaan. Untuk itu, desain lembaga perwakilan disusun dengan mencari keseimbangan antara kebhinekaan dan kesatuan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melambangkan keragaman ideologis warga yang diisi oleh perwakilan aneka partai politik yang (atas usul Hatta) dipilih langsung oleh rakyat. Posisi DPR tidak dipandang sebagai “parlemen” (yang menjadi locus of sovereignty seperti di Inggris); DPR hanyalah lembaga legislatif biasa yang ditempatkan sebagai majelis rendah (lower house).
Penggenggam kedaulatan Rakyat (locus of sovereignty) ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lambang kesatuan semangat kekeluargaan bangsa Indonesia. MPR dipandang sebagai lembaga tertinggi negara (upper house) yang diisi bukan saja oleh perwakilan DPR, namun juga kekuatan-kekuatan strategis rakyat lainnya, yakni utusan daerah dan utusan golongan (kelompok strategis di ruang publik seperti kolektivitas perekonomian, kaum marginal, cendekiawan, dan kelompok bela negara). Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tertinggi, MPR bertugas untuk menetapkan dua kebijakan dasar: UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Tentang prosedur pembentukan utusan daerah dan golongan, Soekiman dan Mohammad Yamin mengusulkan pemilihan secara langsung. Hatta keberatan dengan usul tersebut. Soepomo mengusulkan lewat pemilihan secara tidak langsung, seperti lewat konvensi (permusyawaratan) golongan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang menyerahkan soal pengangkatan utusan golongan itu kepada Presiden.
Dalam menjalankan pemerintahan Negara, Indonesia tidak menganut pemerintahan parlementer. Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan Presiden. Meski demikian, dalam negara kekeluargaan, Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan tidaklah mengembangkan politik sendiri, melainkan sekadar mandataris MPR yang melaksanakan GBHN yang dirumuskan secara musyawarah-kekeluargaan oleh perwakilan segala unsur kekuatan rakyat.
Keseluruhan desain institusi demokrasi itu diletakkan dalam kerangka semangat sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat); dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).