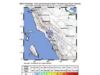Allah Subhanahuwataala berfirman: “Qul huwallahu ahad’. Allahu Somad”
Ayat ini menunjukkan Allah Maha Ahad. Ahad, bukan bermakna bilangan, laiknya pertama. Melainkan ketunggalan. Dia yang Ahad. Ini melingkupi segala urusan. Segala sesuatu. Disitu merupakan wilayah kekuasaan Allah.
Shaykh Abdalqadir as sufi, Rahimullah, berkata: “Manusia modern, jika ditanya, siapa yang menerbangkan burung? Maka dijawab: Tuhan. Tapi siapa yang menerbangkan pesawat terbang boeing? Maka, dijawab: manusia”. Inilah karakteristik modernisme. Tentang adanya dualitas. Bukankah Allahu Ahad? Lantas mengapa modernisme meletakkan paradigma demikian? Tentu ini memiliki kausalitas.
Inilah yang disebut sekulerisme. Yang merupakan anak kandung dari modernisme. Pemisahan antara dua perbuatan: Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Seolah manusia memiliki juga “daya” dan “kehendak”. Tentu ini karakteristik filsafat.
Fakta sejarah bisa menjawab perihal dualitas itu kini mewabah. Manusia, seolah memiliki Qudrah dan Iradah. Modernisme, meletakkan “Qudrah” dan Iradah sepenuhnya berada pada manusia. Tentu, modernism ini merupakan anak kandung rennaisance. Pra rennaisance, “Qudrah” dan Iradah sepenuhnya berada pada Tuhan. Tapi lambat laun, kemudian bergeser. Dan modernisme kemudian mengeliminasi ‘Kebenaran Tuhan’. Hingga yang ada hanya ‘kebenaran manusia’.
Dalih inilah yang membuat seolah urusan hukum, kekuasaan, keuangan, dan lainnya, menjadi mutlak wajib mengikut hasil buah rasionalitas manusia. Tidak lagi mengikut Wahyu. Karena manusia yang dianggap memiliki ‘Daya dan Kehendak’ tadi. Itu korelasinya.
Pra-rennaisance, Tuhan yang berlangsung di Eropa ialah aqidah bak “jabariyya”. Yang kemudian ditafsirtunggalkan oleh Gereja Roma. Hingga memunculkan “the king can do no wrong”. Raja, sebagai wakil Tuhan, dianggap tak pernah salah dan tak bisa salah.
Namun abuse of power kerap berada dalam praktek kerajaan. Tapi tetap saja adagium yang harus dipuja “Vox Rei Vox Dei”, suara Raja suara Tuhan. Jabariyya ini yang melekat tajam masa pra rennaisance. Hingga peristiwa ‘Magna Charta’ di Kerajaan Inggris, mendobrak pakem ‘jabariyya’ di Eropa, tahun 1215. Pelopornya adalah kaum Ordo Ksatria, yang mendapat didikan tassawuf dari pasukan Sultan Salahuddin al Ayyubi, masa Perang Salib berlangsung.
Mereka kembali ke Eropa, dan memunculkan Dinasti Plantegenet, penyambung lidah Raja dan rakyat. Disitulah Inggris berada diluar garis “jabariyya” yang dikomandani Imperium Romanum Socrum. Tapi perlawanan terhadap jabariyya Gereja Roma, meledak kala mencuatnya filsafat, masuk ke Eropa.
Aquinas membawa ajaran Al Farabi, Ibnu Sina, dengan memunculkan “tweez warden theorie”, teori dua belah pedang. Kebenaran ganda. Al Farabi, menyebutnya dengan “emanasi”. Ada Kebenaran ala Wahyu, dan kebenaran ala rasio. Ini yang masa filsafat di-Islam-kan, merebak aliran mu’tazilah. Dari situlah filsafat kemudian masuk ke Eropa, dan memunculkan rennaisance.
Maka, defenisi pun mulai menteorikan. Tuhan, yang sebelumnya ditafsirkantunggal sebagai penyebab segala sesuatu, dengan mufasirnya ialah mutlak Raja dan Gereja, maka didobrak. Galilelo dan Copernicus memulai pendobrakan dari sisi kosmosentris. Masa skolastik itulah yang kemudian mulai menggeser ‘Kebenaran Ilahi’. Lama kelamaan persoalan kausalitas, sebab akibat, dipersepsikan bahwa Tuhan bekerja dalam alam melalui penyebab sekunder. Tuhan dianggap sebagai pembuat jam. Kala jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya.
Inilah persepsi yang dibangun masa rennaisance. Filsafat tentu menjadi pondasi utamanya. Daya dan kehendak, dianggap merupakan bersumber dari manusia.
Francis Bacon, filosof Inggris, menteorikan “Aku Ada (Being), maka Aku Berpikir (think)”. Bacon memulai bahwa ‘kebenaran’ merupakan buah serapan inderawi semata. Inilah filsafat naturalisme. Tuhan, dipersepsikan sebagai penyebab sekunder tadi. Segala ruang gerak yang terjadi dalam alam dunia, disebabkan oleh manusia. Tapi tidak melepaskan peranan Tuhan, yang dianggap sebagai pembuat jam.
Paham ini mulai diminati. Merebaklah rennaisance. Perlawanan pada dogma pun membahana. Filsafat menjadi “agama baru”. Menggantikan otoritas Tuhan, yang selama ini diitafsirtunggalkan oleh otoritas Gereja Roma. Hingga kemudian muncul Rene Descartes. Cogito ergo sumnya, secara resmi mengeliminasi ‘Kebenaran Tuhan’. “Aku Berpikir (think) maka Aku Ada (being).” Kebenaran, kata Descartes, adalah yang mutlak bersumber dari rasio manusia.
Filsafat, oleh Descartes, dianggap sebagai induk segala ilmu. Dimana Tuhan, manusia, alam semesta dan lainnya, merupakan ajang penyelidikan rasio manusia. Disinilah ‘Kebenaran Tuhan’ resmi dieliminasi. Descartes meletakkan Qudrah dan Iradah sepenuhnya pada manusia. Ini yang disebut Imam Ghazali sebagai filosof ateisme.
Beliau, pada masa mu’tazilah merebak dalam Islam, menggolongkan ada tiga jenis filosof: filosof ilahiyyyun (ketuhanan), filosof tabiiyun (naturalism), dan filosof dahriyyun (ateisme). Tentu Descartes dan yang mengekor di belakangnya, tergolong filosof dahriyyun.
Teorinya menyebut, jangan menerima apapun sebagai ‘kebenaran’, jika belum melewati serapan inderawi manusia. Qudrah dan Iradah sepenuhnya mutlak, seolah dianggap sebagai peranan manusia. Tuhan, bukan lagi didudukkan sebagai penyebab sekunder. Melainkan ‘Kebenaran Tuhan’ telah resmi dieliminasi. Tak ada lagi unsur ‘Ketuhanan” dalam persepsi modernitas, sejak teori Descartes itu.
Descartes menceraikan sisi spiritualitas eksistensi dari sisi material, dan dilenyapkan sampai jangkauan luar alam semesta. Dari sinilah seolah azas “free will” menjadi mutlak milik manusia. Manusia yang menentukan segala alur alam semesta.
Thomas Hobbes pun makin menyahuti. Dalam ‘Leviathan’-nya, Hobbes menterjemahkan ‘free will’ sebagai yang rill adalah eksistensi material, dan yang bukan materi, dianggap tidak rill. Manusia, sepenuhnya sebagai ‘penyebab utama’. Tuhan, bukan lagi penyebab.
Azas “free will” ini yang makin membahana dalam urusan kekuasaan.
Filsafat bebas, yang mendasari Machiavelli dalam menteorikan tentang kekuasaan. Penguasa, kata Machiavelli, adalah sesiapa yang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Teori ini menentang ‘Vox Dei Vox Rei’ yang sebelumnya menggema. Kemudian muncul Montesquei yang menteorikan ‘trias politica’. Bahwa kekuasaan dengan tafsir sebagai wakil Tuhan, maka cenderung korup. Makanya harus diawasi oleh system manusia. Itulah yang dikenal eksekutif diawasi legislative, dan diawasi lagi oleh yudikatif. Tanpa lagi memandang otoritas Ilahi.
Jean Bodin makin melengkapi mahzab ‘free will’ dalam kekuasaan. Soverignty ala Bodin, mendudukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan bagaimana kekuasaan berlangsung. Terbebas dari anasir agama di dalamnya. Kedaulatan, kata Bodin, merupakan otoritas manusia yang bersumber dari kehendak manusia. Maknanya, manusia yang menentukan sendiri. Tapi John Locke, masih menganggap bahwa kekuasaan merupakan ‘duel contract’, yang bersumber dari manusia dan Tuhan.
Hingga puncaknya adalah Rosseou, yang menegaskan kekuasaan adalah sepenuhnya ‘kehendak manusia’. Teori kontrak sosial ala Rosseou, resmi mengeliminasi peranan Tuhan, dalam wilayah urusan ketatanegaraan. Rosseou menteorikan bahwa manusia yang menentukan siapa penguasa. Bukan lagi otoritas Ilahi. Dari sinilah modernitas, resmi menemukan bentuknya. Yang puncaknya adalah Revolusi Perancis, 1789, menjadi ajang resmi aplikasi dari modern. Dimulai munculnya modern state. Artinya, free will, menemukan amalan tunggalnya. Manusia memiliki kehendak penuh. Seolah sebagai “being” adalah yang bersumber dari manusia. Otoritas Ilahi resmi disingkirkan. Inilah sekulerisasi.
Dalam wilayah keuangan, hukum dan lainnya, sekulerisasi ini menjadi ajang resmi dan tunggal. Filsafat menjadi induk semangnya. Tidak ada lagi Kebenaran Wahyu. Urusan keuangan, mutlak seolah diatur dan menjadi domain manusia. Alhasil, segelintir kaum, menjadikan pemaksaan selembar kertas, berubah menjadi uang. Inilah kaum bankir, yang memanfaatkan teori “free will” dengan mendomplengi Raja dan head of state dalam modern state, sebagai otoritas pengendali keuangan dan kekuasaan.
Maka, buah dari “free will” pun berubah menjadi pemaksaan. Pemaksaan terhadap teori. Pemaksaan, untuk menerima kertas sebagai uang resmi. Pemaksaan untuk menerima hukum ala rasio, sebagai satu-satunya hukum. Dan pemaksaan lainnya, yang menjadi karakteristik filsafat. Sebagaimana dulu masa mu’tazilah, ketika pemaksaan menjadi unsur terhadap “al mihnah”, dimana semua wajib dipaksa mengakui bahwa Al Quran adalah makhluk. Maka, modernitas pun menemukan bentuk pemaksaan baru pada manusia. Bukan lagi “free will”.
Ini yang disebut dengan post truth. Kebohongan filsafat. Karena Nietszche telah menemukan bagaimana bentuk kebohongan filsafat, yang dianggap sebagai sumber Kebenaran itu. Nietszche menyebutnya dengan nihilisme. Filsafat, katanya, bukan sumber Kebenaran. “Filsafat adalah berhala,” kata Nietszche. Dengan kalimat menggaumnya, “God is dead”, menandakan dengan filsafat, manusia telah “membunuh Tuhan”. Tapi bukan bermakna ‘Tuhan tiada”. Melainkan Nietszche mengumandangkan “fatum brutum ammor fati!”. Cinta pada Takdir. Karena filsafat, telah memisahkan keyakinan manusia pada Takdir. Seolah segala sesuatu, yang dianggap ‘Qudrah dan Iradah’ yang berasal dari manusia, maka yang disebut ‘Takdir” pun tiada. Tapi “ammor fati!” Nietszche, mengembalikan kepercayaan tentang Takdir. Karena Nietszche mengebiri filsafat sebagai ajang Kebenaran. Melainkan hanya melahirkan nihilism.
Martin Heidegger lebih menegaskan lagi. Heidegger menganggap, filsafat hanya melahirkan kebenaran essensialisme. Bukan Kebenaran eksistensialisme. “Dan itu bukan Kebenaran (being),” kata Heidegger. Filsafat, menurutnya, telah memisahkan Kebenaran dari akarnya. Posisi ini yang menggap “the enf of free will”.
Karena “free will” telah melahirkan dualitas dalam kehidupan manusia. Seolah apa yang berlangsung dalam kehidupan di dunia, merupakan “kehendak dan daya” dari manusia. Inilah dualitas, yang bermakna “menduakan Tuhan”. Makanya manusia modern kemudian percaya dengan hukum buatan manusia, system buatan manusia. Termasuk segala wilayah. Kebenaran Tuhan dieliminasi.
Setelah deklarasi “the end of philosophy” dari Heidegger, maka saatnya manusia kembali. Kembali pada pangkal jalan. Dan itu hanya ada dalam Islam. Islam yang Sahihan. Bukan Islam modernitas, atau Islam puritan. Karena Imam al Ghazali telah memberikan jawaban, sejak filsafat merebak dalam masa mu’tazilah dulu, Imam Ghazali telah mewanti. “Jangan memgambil hakekat ajaran agama darinya,” katanya Imam Ghazali. Determination merupakan jawaban atas matinya “free will”.
Manusia harus kembali sebagai “hamba”. Bukan sebagai ‘penentu’. Karena filsafat membawa manusia seolah sebagai “creator”. Sebagai penyebab. Ketika manusia kembali sebagai “hamba”, maka manusia akan menemukan jawabannya. Jawaban atas mekanika kuantum-nya Allah Subhanahuwataala. Disitulah diperlukan ketundukan penuh. Karena segala Qudrah dan iradah, merupakan mutlak domain Tuhan. Bukan domain manusia.
Posisi sebagai ‘hamba’, membawa manusia akan mampu menemukan Tajaliyyat yang berujung pada Mukasyafat. Itulah ma’rifat. Dari filsafat, mustahil manusia akan ma’firat. Karena filsafat, justru membawa manusia seolah sebagai ‘penentu’. Dengen ‘free will’, manusia akan terbawa, seolah itu adalah “buah perbuatanku”. Inilah pondasi system modern.
Tapi dengan determination, maka manusia akan mampu mendapat jawaban, mengapa Tuhan menciptakan manusia dan jin hanya sebagai hamba. Tatkala duduk patuh sebagai hamba, maka kita akan mahfum, mengapa Tuhan menciptakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Karena disitulah keseimbangan alam semesta. Keseimbangan itu, memang harus juga dicerna dengan akal. Tapi bukan akal yang digunakan utama untuk memahami ‘dimana Tuhan’. Akal-nya ala Descartes sampai Newton dan Eisnetein, telah mengeliminasi bahwa ‘Tuhan tiada’. Semua ruang gerak, seolah buah dari ‘perbuatan manusia’. Einstein meyakini, kala dia melempar bola, yang jatuh, itulah dianggap sebagai teori relativitas sosial, yang merpakan “perbuatan dirinya’. Bukan ‘perbuatan Tuhan’.
Alhasil Einstein terjebak bahwa seolah manusia yang ‘melempar’. Padahal bukan ‘engkau yang melempar’. Ketika meyakini ‘aku yang melempar’, maka disitulah kepercayaan kepada Takdir menjadi sirna. Tapi jika meyakini “bukan engkau yang melempar” disitulah posisi kita sebagai hamba,yang menjadi budak-nya Tuhan.
Tentu, itulah kunci memahami Tauhid. Bahwa segala sesuatunya adalah ‘Perbuatan Tuhan’. Allah Subhanahuwataala berfirman: وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ “Padahal Allah-lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu”.
Oleh: Irawan Santoso Shiddiq
Artikel ini ditulis oleh:
Warnoto