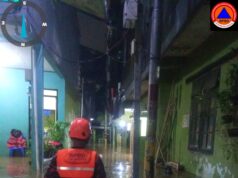Makassar, aktual.com – Hukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samuderanya. Maka kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jikalau samuderanya kering.
Adagium yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dengan tema Budaya Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/9/2024, tersebut membawa pesan yang mendalam mengenai korelasi antara etika dan hukum.
Etika menjadi hulu dari segala problematika terdegradasinya budaya hukum yang berkeadilan, sehingga pada hilirnya terjadi kemerosotan negara di segala aspek, baik aspek demokrasi, sosial, politik maupun perekonomian.
“Sekarang salah satu isu yang paling banyak dibicarakan orang soal etika ini. Ini momentum melakukan pembenahan. Sejak 2009 saya sudah promosikan pentingnya menata sistem etika berbangsa dan bernegara ini,” katanya.
Manusia sebagai penggerak hukum harus dipastikan telah bersih dari nilai-nilai niretika jika ingin
mewujudkan cita-cita budaya hukum yang berkeadilan.
Sebaliknya budaya hukum yang rapuh dan runtuh disebabkan oleh penggerak hukumnya yang tidak lagi membawa nilai-nilai etika dan moralitas, sehingga sistem hukum yang diibaratkan dengan sebuah kapal tidak mampu mencapai dermaga keadilan yang dicita-citakan.
Beberapa problematika budaya hukum yang disebabkan oleh perilaku penyelenggara negara yang niretika tersebut adalah sistem politik yang mengarah pada otoritarianisme.
Sistem politik otoritarianisme ini dapat menjebak penyelenggaran negara pada sikap penghambaan kepada presiden, yang terungkap dengan digunakannya istilah “raja” oleh elit politik.
Sikap penghambaan kepada presiden seperti ini mengakibatkan minimnya pengawasan dan kontrol.
Lembaga Parlemen (legislatif) jauh dari efektif, karena hanya menjadi alat penguasa (eksekutif),
menjadi stempel (rubber stamp) terhadap keputusan eksekutif. Penyalahgunaan konsep politik kekeluargaan, yang direduksi secara sempit sebagai bagi-bagi kue kekuasaan, menyandera mereka yang berseberangan dan kritis terhadap kekuasaan.
“Paling fatal ialah problem otokrasi legalisme, atau kondisi ketertutupan sistem politik terkait upaya manipulasi hukum. Bisa disebut juga dengan despotisme baru. bagaimana pemimpin berupaya untuk menempatkan dirinya lebih tinggi dari kekuasaan lain dengan cara manipulasi atau upaya mempermainkan hukum atas nama menghancurkan rule of law itu sendiri,” kata Airlangga Pribadi, Pakar Politik Universitas Airlangga.
Dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan dan pembenar keinginan rejim yang sedang berkuasa, elit politik tidak lagi berdaya untuk berperan sebagai oposisi. Resultante dari kekisruhan etika dan tekanan politik seperti ini bermuara pada budaya oligarki dalam prikehidupan berpolitik, bernegara dan berbangsa.
Problematika ini pada akhirnya merambat pada kehidupan demokrasi yang cukup serius, diantaranya pembatasan dan ancaman terhadap diskusi akademis di kampus-kampus, pembatasan kontestasi pemilu dengan penerapan threshold yang tinggi sehingga menciptakan koalisi gemuk.
Praktik politik kolutif seperti ini menyebabkan sistem demokrasi hanyalah bersifat prosedural, semakin menjauh dari demokrasi substantif yang seharusnya mengandung unsur representasi publik, rule of law, right and responsibility, dan partisipasi publik.
“Sistem pemilu kita melemahkan budaya politik dan budaya hukum sekaligus karena memang begitu rumit, mahal, sibuk dan juga tidak sempat bicara politik gagasan dan akhirnya menjauhkan akses politik minoritas dan marjinal,” ujar Titi Anggraini, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perluden) yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kerapuhan etika juga terjadi pada aspek hukum. Hukum tidak disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi kepentingan politik praktis dan modal. Hal ini dapat dilihat dari, misalnya, pengesahan Omnibus law lebih cepat daripada UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang belum disahkan hingga saat ini.
Dalam penegakan hukum sendiri, sistem reward dan punishment tidak dilakukan dengan efektif di lingkungan peradilan Indonesia sehingga mendegradasi integritas penegak hukum.
Koruptor pun tidak benar-benar diberikan hukuman yang mengisolasi mereka dari akses kepada publik sehingga membuat mereka tetap bisa tampil di depan public tanpa rasa malu.
“Salah satu poin penting sistem hukum ialah independensi peradilan dan integritas aktor peradilan. Hari ini kita bisa saksikan bagaiman hukum apa kata tujuan pemegang kekuasaan,” ujar Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII).
Seluruh kerapuhan etika dan moralitas hukum ini mengakibatkan akar skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2023 menjadi 34/100, sama dengan skor pada 2022.
Dengan skor ini, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.Pertumbuhan CPI Indonesia pada Juli 2023 adalah 3,1% year-on-year (YoY), turun dari 3,5% pada bulan sebelumnya.
Tapi yang lebih menyedihkan adalah dalam konteks Index Demokrasi Indonesia masuk ke dalam kategori negara flawed democracy, negara demokrasi yang belum sempurna dan cacat.
Ada 48 negara masuk dalam kategori ini. Jika skor ini dikaitkan dengan CPI, negara-negara yang masuk kategori flawed democracy rata-rata CPI nya 48, dan Indonesia skornya 34.
Peringkat Indonesia ini memberi sinyal berbahaya, sebab jika ke depan tergelincir 2 skor saja ke bawah, Indonesia akan dikategorikan sebagai negara non-democratic countries dan government sekaligus.
“Saya wanti-wanti penegakan antikorupsi. Ottoman empire hancurnya karena korupsi. Kalau kita masih seperti ini korupsinya, kehancuran bisa terjadi pada diri kita,” tutur Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019.
Ketika ketiadaan etika penyelenggara negara menjadi sesuatu yang sistemik, terlebih didukung oleh perangkat digital, maka yang akan muncul adalah premanisme politik dan hukum yang menggunakan perangkat buzzer media.
Perangkat media digital berhasil merekayasa popularitas pejabat dan kebijakan, seolah-olah kebijakan tersebut telah disetujui oleh Masyarakat secara luas, padahal merupakan bentuk hegemoni kepentingan penguasa dan menjadi pertanda demokrasi yang telah hampir mati.
Hal ini yang menyebabkan implementasi sistem nilai etika tidak cukup hanya dilakukan sebatas aspek sosial kultural, namun juga harus dilakukan secara simultan dengan perbaikan dalam aspek struktural.
Pergerakan etika secara struktural dalam bentuk kebijakan telah dilegitimasi secara ilmiah oleh perkembangan etika. Perbaikan etika tidak lagi cukup hanya diwacanakan sebagai sebuah diskursus keilmuan filsafati yang disuarakan melalui mimbar-mimbar keagamaan maupun
akademis, namun harus dipositivisasi.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika sudah seharusnya tidak lagi diperdebatkan secara filsafati. Pancasila seharusnya dipedomani sebagai sebuah falsafah (weltanschauung) yang dijunjung tinggi demi menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan beradab.
“Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, dibawahnya ada undang-undang (UU) yang mengatur segala aspek. Mestinya, Pancasila sudah masuk ke segala sektor kehidupan,” kata Harjono, Hakim Konstitusi 2003-2014.
Oleh karena itu positivisasi etika harus dilakukan dalam bentuk code of ethics dan enforcement system of ethics dalam bentuk infrastruktur the ethic for public offices.
Sudah saatnya etika harus dikonkritisasi dalam bentuk aturan tertulis lengkap dengan instrumen dan struktur penegakannya. Etika jangan dibiarkan hanya menjadi sebuah norma kesusilaan yang menguap begitu saja.
Positivisasi etika tersebut menjadi penting dan mendesak (important and urgent) yang secepatnya harus dilakukan di tengah gempuran perkembangan zaman yang lebih mengedepankan logika daripada rasa, hati nurani dan adab.
Gempuran budaya pop mengakibatkan terdegradasinya nilai-nilai budaya Indonesia yang penuh dengan sopan santun, rasa malu, kejujuran, satria, dan welas asih. Sistem keteladanan etika harus dimulai dulu dari penyelenggara negaranya, baru akan mudah bagi masyarakat untuk mengikuti.
Krisis keteladanan penyelenggara negara menjadikan penanaman nilai integritas pada Masyarakat menjadi sulit.
Bagaimana bisa mengkapitalisasi kualitas bonus demografi jika anak muda dipolitisasi menjadi buzzer dan dijauhkan dari nilai-nilai etika.
“Tidak pernah ada upaya signifikan untuk meningkatkan anak muda. Bahkan sering dikatakan akan ada Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kan besok akan seperti apa, sekarang kondisi kita sepetti apa, kemudia dibuat modifikasi seperti apa untuk mencapai itu. Ini sama sekali tidak ada, yang ada hanyalah anak muda yang digunakan sebagai influencer,” kata Koentjoro, Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada.
Pada akhirnya penegakan ssstem etika harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat baik penyelenggara negara sebagai tauladan hingga masyarakat umum.
Berdasarkan problematika tersebut diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut :
Hukum:
1. Perlu dibentuk undang-undang Lembaga Kepresidenan yang mengatur etika
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, khususnya etika pada masa transisi
jabatan (lame duck period).
2. Dalam merumuskan hukum harus mengedepankan supremasi etika, bukan sekedar
supremasi hukum sehingga yang tercipta benar-benar rule of law yang berkeadilan dan
sesuai dengan nilai-nilai etika, bukan rule of man by using law, bukan hukum dibuat
sebagai sarana perselancaran niat terselubung atas kepentingan tertentu.
3. Perlu pembentukan UU tentang Etika Berbangsa dan Bernegara dan Mahkamah Etika
Nasional. Keduanya menjabarkan 6 substansi etika dalam TAP MPR 6/2001 dan
infrastruktur pendukungnya.
Politik dan Kebijakan:
1. Pembentukan sistem yang terpisah antara peradilan hukum dan peradilan etika
sehingga tidak terjadi fenomena peradilan hukum mengoreksi dan mendistorsi putusan
peradilan etika seperti yang terjadi pada kasus penetapan sanksi etis oleh Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang
dianulir putusannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Mengkonseptualisasi sistem etika pejabat publik mulai dari etika penyelenggara negara
sampai pada organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial
keagamaan, organisasi politik, lembaga pendidikan, organisasi kebudayaan, dunia usaha,
serta para pemangku kepentingan dalam segala aspek kehidupan masyarakat di
Indonesia.
3. Mengembalikan politik dan kebijakan berbasis intelektualitas dengan pelibatan para
intelektual, scholars, cendekiawan, bukan kebijakan berbasis viralitas dan hegemoni para
buzzer.
4. Memberantas pemborosan impor dan kapitalisasi sumber daya pangan secara besar-
besaran yang membunuh produksi dalam negeri dan kesejahteraan produsen dalam
negeri karena imbalan ekonomi dari importir asing yang diberikan kepada para elit politik.
5. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas
isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti pemanasan global, eksploitasi
tanah, bahan bakar fosil dan lain sebagainya.
6. Perlu mengembangkan daya kritis masyarakat sebagai upaya pengawasan terhadap
pemerintah dan penyelenggara negara, jangan ada pengkultusan terhadap pemimpin
sehingga rakyat membabi buta dalam penghambaan diri terhadap pimpinan dengan
harapan balas budi dari pemimpin.
7. Pemiskinan sosial secara sistemik perlu dihentikan, jangan sampai ada sekelompok orang
yang karena terlalu kaya bisa membeli suara mereka yang terlalu miskin.
8. Perlu sinergi antara aktivisme sosial, hukum dan digital sehingga terhubung antara issue
dan sector sebagai upaya sinergitas dan pendekatan sistematis yang tidak sporadis
dalam menghadapi kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat.
9. Pemberian hukuman berupa pencabutan hak-hak politik tanpa toleransi dan pembatasan
hak-hak keperdataan kepada koruptor sehingga meminimalisasi akses koruptor untuk
tampil dan berkontestasi menjadi pejabat publik.
Pendidikan:
1. Meningkatkan efektivitas bonus demografi dengan perbaikan kualitas generasi emas
melalui pembekalan pada kompetensi kognitif dan afektif (etika dan moralitas) secara
integral.
2. Perlunya pendidikan kritis dan reflektif yang membangun kepercayaan terhadap nilai-nilai
yang lebih objektif, terbuka dan memancing dialektika dibandingkan kepercayaan absolut
membabi buta terhadap orang/individu atau buzzer. Konsekuensinya adalah terjalin
hubungan yang egaliter dan terciptanya kebebasan mimbar akademik di universitas,
sekaligus memulihkan makna kepakaran.
Partai Politik dan Sistem Pemilu:
1. Revisi UU Partai Politik untuk mengakomodir Sistem Integritas Partai Politik (SIPP),
menegakkan desentralisasi politik, dan mengembalikan kedaulatan anggota partai.
2. Reformasi sistem pendanaan politik melalui alokasi anggaran negara yang lebih
transparan dan akuntabel untuk pembiayaan parpol guna menopang program kaderisasi,
rekruitmen politik melalui pemilihan internal, serta penerapan syarat minimal sebagai
kader selama waktu tertentu untuk pengisian jabatan politik.
3. Kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang menuju
koherensi dan konsistensi pengaturan hukum pemilu di Indonesia.
4. Evaluasi sistem pemilu dan model keserentakan pemilu. Pemilu dilakukan dengan
dua model keserentakan: Pemilu Serentak Nasional (memilih presiden dan wakil
presiden, anggota DPR, serta anggota DPD) dan Pemilu Serentak Lokal (memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota),
dengan masa jeda 2 (dua) tahun. Agar mesin partai selalu bekerja serta pemilih bisa
mengevaluasi kinerja partai dan elite politik secara berkesinambungan.
5. Menetapkan ambang batas jumlah anggota pendukung koalisi partai hingga tidak tercipta
oligarki politik yang membahayakan proses berpolitik dan pengambilan kebijakan yaitu
dengan ambang batas paling besar 60% dari seluruh partai politik yang mengisi parlemen.
6. Pengesahan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk memotong mata rantai jual
beli suara di pemilu dan pilkada.
7. Rekonstruksi persyaratan ambang batas pencalonan presiden untuk mengurangi dan
menghilangkan hambatan dalam pencalonan dan menghadirkan kontestasi elektoral yang
lebih inklusif.
8. Mengatur masa transisi kepemimpinan nasional (lame duck period) guna mencegah
kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada masa transisi
pascapemilu nasional. Masa jeda antara hasil pemungutan suara dan pelantikan calon
terpilih dibuat tidak terlalu lama.
9. Partai-partai politik diharapkan memprioritaskan kader-kader yang memahami persoalan
daerah dan mewakili daerahnya dalam sistem meritokrasi.
BPIP:
1. Tidak optimalnya badan kehormatan dan dewan etik pada berbagai lembaga negara
mendorong BPIP untuk menginisiasi rancangan UU Etika yang merumuskan pokok-pokok
etika secara materil hingga instrumen formilnya, seperti sistem penegakan hukum pada
peradilannya hingga sanksi yang dikenakan.
2. BPIP perlu melakukan pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara baik kepada
kepada para pekerja migran, pelajar/mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan
di luar negeri, dan WNI lainnya yang tinggal di luar negeri maupun masyarakat Indonesia
yang ingin kembali ke Indonesia, untuk memastikan WNI tersebut tidak terpengaruh oleh
ideologi-ideologi asing/transnasional.
3. Perlu dilakukan Pembinaan dan Pendidikan Pancasila bagi seluruh ASN secara
berjenjang dan berkelanjutan.
4. Perlu melakukan kajian terkait implementasi dari substansi pasal 30 UUD NRI Tahun 1945
tentang Bela Negara dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila di segala lapisan
masyarakat Indonesia.
5. BPIP perlu mendorong pembumian Pancasila dalam konteks budaya hukum dan
independensi peradilan agar semangat kesetaraan yang diusung dalam Pancasila dan
solidaritas seluruh rakyat bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan integritas
penegak hukum dan independensi lembaga peradilan.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano