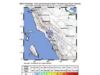Jakarta-Aktual.com – Suara lirih terdengar dari seorang pria jangkung kurus berambut panjang. “Sekarang sepi, pak. Orang belanja perlengkapan outdoor enggak kayak dulu. Sekarang bisa nutup duit kontrakan kios saja udah lumayan,” ujar Ranu.
Ranu adalah nama panggilan yang juga dia sematkan untuk kios berjualan beragam keperluan adventure bagi para pecinta alam dan aktivitas ekstrim di seputaran Cibinong, Kabupaten Bogor. Ranu tidak sendiri. Dia bercerita, kondisi serupa juga dialami beberapa rekannya yang menggeluti usaha yang sama.
“Banyak yang tutup,” kata dia.
Cerita Ranu adalah satu dari sekian banyak potret ekonomi riil yang kini terasa semakin dingin. Ia bukan sekadar keluhan personal, tapi gema dari gejala struktural yang menggerogoti perekonomian nasional.
Kisah Ranu rupanya senada dengan pernyataan mengejutkan yang datang dari Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono. Ia menyebut bahwa ekonomi Indonesia terus menurun, bahkan berada di titik terendah sejak tahun 1970-an. Pernyataan Dicky memang tidak sepenuhnya mewakili Bank Indonesia di mana dia mengabdi. Dia menyampaikan hal tersebut saat uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI, Selasa 1 Juni 2025, di Senayan, Jakarta.
Bukan sekadar alarm, kondisi saat ini adalah sirene panjang tanda darurat. Dan yang lebih ironis, peringatan itu keluar di tengah gelombang optimisme politik yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir dengan gagasan besar yang mereka sebut “Astacita”, delapan cita-cita besar bangsa. Visi mereka menggelora: industrialisasi, swasembada pangan, hilirisasi tambang, makan bergizi gratis. Namun realitas di lapangan jauh dari gegap gempita.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan lebih dari 26 ribu tenaga kerja terkena PHK hingga Mei 2025. Apindo bahkan memperkirakan jumlahnya mendekati 74 ribu. Di balik angka itu, ada wajah-wajah cemas para buruh pabrik, karyawan startup, dan supir logistik yang kini mengisi antrean panjang kartu kuning.
Kelas menengah, yang digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan konsumsi, justru mulai runtuh. Survei T-REC menunjukkan hampir 49 persen dari mereka mengalami penurunan daya beli. Banyak dari mereka yang dulu mampu membeli barang bermerek, kini mulai berhitung ulang untuk sekadar belanja mingguan.
Lalu, bagaimana mungkin negara yang ekonominya melemah bisa mengejar target pertumbuhan delapan persen?
Apakah mimpi besar bisa berdiri di atas pondasi yang retak?
Pemerintah mencoba menjawab dengan efisiensi fiskal. Pemangkasan anggaran senilai Rp306 triliun diumumkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pendingin ruangan di kantor kementerian dimatikan. Perjalanan dinas dipangkas. Proyek infrastruktur direm. Namun efisiensi yang tak disertai strategi pemulihan malah memperlambat perputaran uang di daerah.
Gibran, yang semula digadang menjadi ikon muda penuh terobosan, kini lebih sering terlihat mengunjungi acara makan gratis dan menyapa anak-anak sekolah. Ia belum tampak sebagai motor penggerak arah kebijakan ekonomi. Padahal, rakyat menunggu lebih dari sekadar senyum ramah dan konten viral.
Sementara itu, koordinasi antarkementerian berjalan dengan tempo masing-masing. Kabinet yang gemuk justru menambah beban birokrasi. Banyak kebijakan strategis kehilangan arah karena tidak punya komando yang jelas. Di tengah turbulensi global, Indonesia butuh nahkoda, bukan sekadar kru kapal yang sibuk memoles dek.
Yang paling mengkhawatirkan adalah menyusutnya kelas menengah. Dalam lima tahun terakhir, hampir 10 juta orang terlempar dari zona aman menuju jurang rentan. Mereka kehilangan pekerjaan, tak lagi mampu mencicil rumah, bahkan terpaksa menarik anak dari sekolah swasta. Jika mereka tak dipulihkan, maka krisis ini tak hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga kehancuran harapan.
Kritik terhadap kebijakan ekonomi bukan untuk menjatuhkan. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan nurani agar negara meninjau ulang peta jalannya. Janji tanpa realisasi adalah utopia. Realisasi tanpa empati adalah otoritarianisme ekonomi.
Pemerintah perlu mengubah pendekatan. Pertama, evaluasi mendalam terhadap program makan gratis, apakah ia berdampak langsung pada gizi dan angka partisipasi sekolah, atau sekadar konsumsi populis?
Kedua, Gibran harus turun langsung dalam komunikasi kebijakan, tidak hanya sebagai wajah muda tapi juga sebagai otak muda.
Ketiga, anggaran harus mengalir ke sektor produktif UMKM, pertanian, dan manufaktur padat karya. Insentif fiskal bisa menyasar pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Keempat, hilirisasi tak boleh hanya mengejar ekspor nikel mentah, tapi juga membangun rantai pasok yang berpihak pada nilai tambah domestik.
Terakhir, dan yang paling penting: bangun kembali kepercayaan rakyat. Buka data, jujur soal capaian dan tantangan. Akui kelemahan, perbaiki dengan kerendahan hati. Rakyat tidak butuh pemimpin sempurna, mereka hanya ingin dipimpin oleh yang mau mendengar.
Cerita-cerita seperti itu bukan hanya anekdot. Mereka adalah alarm sosial. Pemerintah harus peka. Karena jika tidak, yang runtuh bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Tapi kepercayaan. Dan kalau itu yang terjadi, tidak akan ada astacita yang mampu menyelamatkan kita.
Bangsa besar adalah bangsa yang berani bercermin. Kita belum terlambat. Tapi waktu terus berjalan. Dan keheningan terlalu mahal untuk dibayar dengan derita rakyat.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto