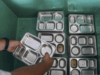Jakarta, aktual.com – Dalam pandangan Islam, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya bukanlah entitas netral yang berdiri di luar relasi manusia. Alam adalah ciptaan Allah Swt. yang mengandung tanda-tanda kebesaran-Nya (āyāt kauniyyah), sehingga relasi manusia dengan alam bersifat teologis, bukan semata ekonomis. Karena itu, kerusakan alam tidak dapat dipahami hanya sebagai problem teknis atau kebijakan, melainkan juga sebagai persoalan moral dan spiritual.
Al-Qur’an secara tegas menempatkan manusia sebagai khalīfah di bumi. Allah Swt. berfirman:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (QS. al-Baqarah [2]: 30)
Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan wakil yang diberi mandat. Kekhalifahan tidak bermakna dominasi tanpa batas, tetapi amanah untuk mengelola, menjaga, dan memastikan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak tatanan alam sejatinya merupakan pengkhianatan terhadap amanah ilahiah tersebut.
Dalam ayat yang sama, para malaikat mempertanyakan potensi manusia yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah:
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
Kekhawatiran malaikat ini mengandung peringatan laten bahwa kecenderungan fasād merupakan ancaman nyata dalam sejarah kemanusiaan. Namun Allah menjawab:
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Jawaban ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi moral dan spiritual untuk menjaga bumi—namun potensi tersebut hanya terwujud jika amanah kekhalifahan dijalankan secara bertanggung jawab.
Larangan melakukan kerusakan di muka bumi ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. al-A‘rāf [7]: 56)
Kata الفساد (al-fasād) dalam ayat ini oleh para ulama tidak dipahami secara sempit. Imam Fakhruddin al-Rāzī dalam Mafātīḥ al-Ghayb menjelaskan bahwa fasād mencakup segala bentuk perusakan yang menghilangkan kemaslahatan hidup, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Jika ditarik ke dalam konteks kontemporer, kerusakan lingkungan—seperti penggundulan hutan, pencemaran sungai, eksploitasi tambang berlebihan, dan alih fungsi lahan tanpa kendali—jelas termasuk kategori fasād yang dilarang secara syar‘i.
Al-Qur’an juga mengaitkan secara langsung antara kerusakan alam dan perbuatan manusia:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. ar-Rūm [30]: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa bencana ekologis bukan sekadar fenomena alamiah yang netral secara moral, melainkan memiliki dimensi etis dan teologis. Kerusakan alam adalah cermin dari krisis nilai, keserakahan, dan kegagalan manusia memahami batas perannya di hadapan Allah.
Ibn Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa fasād di darat dan laut mencakup rusaknya pertanian, berkurangnya hasil panen, dan hancurnya keberkahan alam akibat kemaksiatan manusia. Bahkan Abū al-‘Āliyah menegaskan:
مَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ
“Barang siapa bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di bumi.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kerusakan moral dan spiritual. Ketika manusia memutus relasi etisnya dengan Tuhan, dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan ekologis.
Dalam kerangka fiqh ekoteologis, menjaga alam—termasuk hutan, sungai, dan seluruh ekosistem—adalah bagian dari ibadah. Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan penyangga kehidupan (ḥāfiẓ al-ḥayāh): penjaga air, pengendali iklim, dan rumah bagi makhluk Allah lainnya. Merusaknya berarti merusak sistem kehidupan yang telah Allah ciptakan dengan keseimbangan (mīzān).
Karena itu, Islam tidak membenarkan eksploitasi alam yang melampaui kebutuhan dan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh menimbulkan bahaya dan saling membahayakan) menjadi dasar etika ekologis yang kuat dalam Islam.
Dengan demikian, krisis lingkungan sejatinya adalah krisis teologis. Ia menuntut pertobatan ekologis (tawbah bī’iyyah), perubahan cara pandang, dan penguatan kesalehan ekologis. Manusia hanya akan mampu menjadi khalifah sejati jika ia mampu menjaga bumi sebagai amanah, bukan menjarahnya sebagai penguasa absolut.
Wallāhu a‘lam bi al-ṣawāb.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain