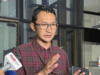Oleh: M. Ikhsan Tualeka (Pegiat Perubahan Sosial)
Jakarta, aktual.com – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat setelah sejumlah elite politik menyampaikan pandangan bahwa mekanisme tersebut akan mempermudah pengawasan terhadap praktik politik uang.
Dengan dalih efisiensi dan kemudahan kontrol, Pilkada melalui DPRD diposisikan sebagai solusi atau ‘exit path’ atas mahalnya demokrasi elektoral. Argumen yang sekilas, terdengar rasional.
Namun, di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi partai politik (politisi) dan parlemen, gagasan tersebut justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar.
Sebab persoalan Pilkada bukan semata soal teknis pemilihan, melainkan soal bagaimana kekuasaan diproduksi, didistribusikan, dan kepada siapa kekuasaan itu akhirnya bertanggung jawab.
Pandangan bahwa mengawasi 20–30 anggota DPRD lebih mudah dibanding mengawasi jutaan pemilih mengandung penyederhanaan atau simplifikasi yang justru berbahaya.
Politik uang tidak bekerja berdasarkan logika kuantitas semata, melainkan melalui relasi kuasa, struktur insentif, dan watak institusi politik.
Dalam banyak kasus, justru ketika kekuasaan terkonsentrasi pada sedikit aktor, praktik transaksional menjadi lebih rapi, lebih efisien, dan jauh lebih sulit disentuh atau dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal.
Alih-alih memberantas politik uang, Pilkada melalui DPRD berpotensi besar menggeser dan memusatkan praktik tersebut ke ruang yang lebih sempit, tertutup, dan elitis, yakni ke dalam partai politik, politisi dan fraksi-fraksi DPRD.
Dari praktik yang sebelumnya relatif kasatmata di ruang publik yang terkadang riuh oleh sorak-sorai, kita berisiko beralih ke politik transaksi yang senyap dan terlembagakan.
Dalam konteks ini, politik uang sejatinya tidak dihapus atau dinihilkan, melainkan “ditertibkan” agar tidak mengganggu stabilitas elite dan tidak memancing kegaduhan publik.
Pengalaman politik elektoral Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa problem politik uang tidak pernah sepenuhnya berada di tingkat pemilih atau konstituen.
Bahkan dalam sistem Pilkada langsung, praktik tersebut justru telah lama berakar di hulu, yakni dalam proses kandidasi di internal partai.
Telah menjadi rahasia umum, untuk memperoleh rekomendasi pencalonan, banyak kandidat harus berhadapan dengan realitas mahar politik—praktik yang kerap dibungkus dengan istilah sumbangan, komitmen logistik, atau kesepakatan politik.
Proses kandidasi menjadi mahal, eksklusif, dan sangat ditentukan oleh selera elite, bukan oleh kualitas kepemimpinan, rekam jejak pengabdian atau faktor lain yang lebih mendasar.
Jika dalam Pilkada langsung saja mahar politik demikian kuat, sulit membayangkan bahwa praktik tersebut akan hilang atau setidaknya berkurang ketika seluruh proses pemilihan kepala daerah diserahkan sepenuhnya kepada DPRD.
Justru yang terjadi bukanlah pengawasan yang lebih mudah, melainkan konsentrasi transaksi pada segelintir aktor.
Artinya, biaya politik tidak menghilang, malah akan lebih meningkat karena yang diperebutkan adalah suara mereka yang memiliki kewenangan menentukan. Politik uang tetap mengemuka, tetapi menjadi lebih efisien karena tidak lagi menyasar publik luas, melainkan cukup mengamankan elite yang tepat.
Dalam skema ini, suara rakyat tidak lagi dibeli secara masif dan vulgar, tetapi ditukar secara eksklusif melalui lobi, kesepakatan fraksi, kompromi antar-partai, elite dan kandidat.
Politik uang tidak lenyap, melainkan bermetamorfosis menjadi praktik yang lebih halus dan sulit dilacak. Dalam situasi semacam ini demokrasi kehilangan fungsi korektifnya karena publik tersingkir dari proses paling menentukan dalam sirkulasi kekuasaan lokal.
Memang tidak dapat disangkal bahwa Pilkada langsung juga menyimpan banyak persoalan. Biaya politik yang relatif tinggi, politik identitas seringkali mengemuka, dan populisme instan kerap mencederai kualitas demokrasi.
Namun, Pilkada langsung tetap menyediakan satu elemen mendasar yang tidak tergantikan: ruang partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Dalam sistem ini, kepala daerah—baik atau buruk—setidaknya harus atau tetap mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada pemilih yang memberinya mandat. Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD akan menggeser orientasi pertanggungjawaban tersebut.
Kepala daerah terpilih akan lebih terikat pada partai dan anggota Dewan yang memilihnya. Loyalitas politik pun berpindah, dari rakyat ke elite.
Dalam praktiknya, kepala daerah akan lebih sibuk menjaga keseimbangan kepentingan partai politik dan fraksi-fraksi ketimbang membangun akuntabilitas kepada warga. Di titik inilah demokrasi mengalami degradasi yang tidak selalu tampak kasat mata: dari demokrasi partisipatif menuju demokrasi transaksional.
Pendukung Pilkada lewat DPRD kerap berargumen bahwa mekanisme ini membuka peluang bagi figur-figur potensial yang tidak populer atau tidak bermodal besar. Argumen yang sepertinya terdengar ideal, tetapi faktanya, itu kurang berpijak pada realitas politik Indonesia saat ini.
Partai politik belum sepenuhnya dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Tanpa reformasi serius di tubuh partai, mekanisme pemilihan oleh DPRD justru berisiko memperkuat atau melestarikan praktik dagang sapi politik.
Kursi kepala daerah menjadi komoditas yang dinegosiasikan, ditukar dengan jabatan, jatah proyek, atau konsesi kebijakan. Semua berlangsung sesuai kepentingan elite, bukan berdasarkan kepentingan publik.
Dalam konteks seperti ini, klaim bahwa pengawasan terhadap 20–30 anggota DPRD lebih mudah patut dipertanyakan. Pengawasan justru menjadi semakin politis karena relasi kuasa saling bertaut dan saling mengamankan.
Aparat penegak hukum kerap baru hadir setelah kerusakan dan praktik penyalahgunaan kekuasaan terjadi, sementara proses transaksional terus berlangsung di ruang yang nyaris steril atau terhalang dari sorotan publik. Benar bahwa secara konstitusional, baik Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama sah.
UUD 1945 hanya mensyaratkan pemilihan dilakukan secara demokratis. Namun, konstitusionalitas itu harus berpijak atau melihat pada kemajuan dan masa depan demokrasi. Banyak praktik yang sah secara hukum, tetapi regresif secara politik. Pertanyaan utamanya bukan sekadar boleh atau tidak, melainkan ke arah mana demokrasi lokal Indonesia sedang diarahkan.
Tidak bisa diabaikan pula bahwa sejauh ini, dukungan terhadap Pilkada lewat DPRD terutama datang dari aktor dan partai politik yang telah mapan dalam struktur kekuasaan.
Bagi mereka, mekanisme ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal kontrol. Dengan mempersempit arena pemilihan, kekuasaan menjadi lebih mudah dikelola, dinegosiasikan, dan dilanggengkan dalam lingkaran terbatas.
Rakyat, dalam logika ini, tidak lagi ditempatkan sebagai subjek demokrasi, melainkan sebagai variabel yang dianggap mahal, tidak pasti, dan berpotensi mengganggu stabilitas.
Jika problem utama Pilkada adalah politik uang, maka solusinya bukan dengan memindahkan arena transaksinya ke ruang yang lebih tertutup. Jalan keluarnya justru terletak pada pembenahan mendasar: transparansi pendanaan politik, demokratisasi internal partai, serta penegakan hukum yang konsisten dan berani.
Tanpa itu semua, perubahan mekanisme hanya akan menjadi kosmetik institusional. Karena akar masalah utama yang bersemayam di partai politik tidak dicabut atau dibenahi. Pilkada lewat DPRD pada akhirnya bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pilihan politik tentang siapa yang memegang kedaulatan.
Politik uang mungkin tidak lagi berisik di jalanan, lewat serangan fajar atau model pembelian pengaruh lainnya, tetapi justru semakin mapan di ruang-ruang kekuasaan—tenang, rapi, dan sulit disentuh atau dijangkau publik.
Itu artinya, bila pemilihan langsung oleh rakyat akhirnya benar-benar berpindah ke tangan partai atau para politisi di DPRD, maka demokrasi lokal kita sejatinya bukan sedang diselamatkan, melainkan perlahan kehilangan maknanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain