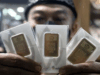Oleh: M. Ikhsan Tualeka – Direktur Eksekutif Indonesian Political Party Watch (IPPW)
Jakarta, aktual.com – Perdebatan ihwal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold merupakan elemen penting dalam sistem pemilihan umum (pemilu) kembali membuka paradoks lama demokrasi elektoral Indonesia.
Di satu sisi, negara dituntut dapat menyelamatkan atau tetap mengakomodir setiap suara rakyat, namun di sisi lain, parlemen tentu saja membutuhkan struktur kerja yang efektif dan
stabil.
Berdasar Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, partai politik peserta pemilu harus
mencapai perolehan suara sah sekurang-kurangnya 4 persen secara nasional untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
Dengan kata lain, sistem ambang batas 4 persen ini, menjadi penentu apakah sebuah partai politik bisa atau tidak mendapatkan kursi di parlemen.
Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023
telah menjadi momentum penting untuk menata ulang paradoks tersebut, meski jalan keluarnya masih terus diperdebatkan.
Dalam putusan itu MK mensyaratkan agar di Pemilu 2029 nanti pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) melakukan perubahan atas norma ambang batas parlemen dan/atau besar persentasenya sesuai dengan prinsip konstitusi.
MK menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan yang adil dan proporsional, jika dipaksakan tanpa kajian metodologis yang memadai.
Dalam konteks ini MK sepakat ambang batas 4 persen tidak memiliki rasionalitas yang memadai, tetapi tidak serta-merta MK menolak konsep ambang batas itu sendiri.
Menanggapi dan memaknai putusan MK, Partai Amanat Nasional (PAN) kemudian
mengusulkan untuk mengganti ambang batas parlemen dengan pembentukan fraksi
gabungan dari partai-partai kecil. Satu gagasan yang sejatinya lahir dari kegelisahan yang sah dan berdasar.
Dalam teori demokrasi representatif, suara pemilih bukan sekadar preferensi elektoral, melainkan mandat politik. Ketika jutaan suara hilang karena ambang batas, legitimasi representasi ikut tergerus.
Namun, sejumlah kalangan juga memberikan catatan kritis. Sebagaimana diingatkan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, bahwa menyelamatkan suara rakyat tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan koherensi politik.
Fraksi gabungan lintas partai kecil yang berbeda ideologi ia sebut sebagai “kawin paksa” politik—sebuah istilah yang tajam, tetapi tidak berlebihan. Logis atau masuk akal.
Dalam literatur ilmu politik, Hanna Pitkin menggambarkan atau membedakan representasi sebagai standing for (kehadiran wakil) dan acting for (bertindak mewakili kepentingan).
Meminjam perspektif itu fraksi gabungan yang menggabungkan partai dengan perolehan kursi yang relatif kecil digabungkan atau dibentuk semata demi memenuhi syarat administratif mungkin berhasil menghadirkan wakil secara formal, tetapi belum tentu mampu bertindak secara substantif.
Tanpa kesamaan nilai dan orientasi kebijakan, fraksi mudah terjebak pada kompromi minimum yang miskin arah. Menjadikan fraksi gabungan itu hanya ada secara struktural, tapi bakal minim peran atau kontribusi secara fungsional.
Belajar dari pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa efektivitas parlemen tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai, tetapi oleh tingkat pelembagaan partai itu sendiri.
Samuel P. Huntington menyebut pelembagaan sebagai prasyarat stabilitas politik—di mana organisasi politik harus memiliki identitas, nilai, dan pola perilaku yang relatif mapan.
Fraksi yang menyatukan partai-partai dengan watak ideologis berbeda justru berpotensi melemahkan atau mengurangi bobot pelembagaan tersebut.
Di Indonesia, persoalan ini menjadi lebih kompleks dan krusial karena konteks multikultural. Dalam konteks ini partai politik tidak hanya mewakili kepentingan elektoral, tetapi juga ekspresi identitas sosial dan ideologis yang beragam.
Memaksa partai-partai kecil dengan latar berbeda-berada dalam satu fraksi bukan hanya soal teknis parlemen, melainkan berpotensi mengaburkan pilihan politik pemilih itu sendiri.
Risiko lain yang mengintai adalah apa yang disebut sebagai decision paralysis. Fraksi gabungan dengan spektrum ideologi yang terlalu lebar rawan mengalami kebuntuan dalam menyikapi isu-isu strategis. Akan kerap terjadi deadlock.
Alih-alih memperkuat fungsi legislasi, fraksi semacam ini justru dapat menjadi arena
tarik-menarik internal yang melelahkan dan tidak produktif. Keberadaannya menjadi tidak efektif.
Di sisi lain, mempertahankan ambang batas parlemen dalam bentuk angka persentase juga menyimpan problem serius. Ambang batas 4 persen terbukti menyingkirkan belasan juta suara sah yang telah mengarahkan pilihan politiknya.
Lebih fatal lagi bila ada lapisan ideologi yang terwadahi lewat partai politik dan memilih bertarung secara elektoral, kemudian gagal melenggang ke parlemen, berpotensi untuk menyalurkan aspirasi politik lewat parlemen jalanan: demonstrasi, atau bahkan dalam pilihan politik yang inkonstitusional.
Dalam rentang perdebatan ini, usulan agar ambang batas didasarkan pada kapasitas
fungsional partai di DPR—misalnya kemampuan mengisi alat kelengkapan
dewan—menawarkan pendekatan yang lebih institusional dan relevan.
Logikanya sejalan dengan teori functional representation: representasi tidak berhenti pada kehadiran, tetapi pada kemampuan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan secara efektif sesuai dengan madat lembaga parlemen.
Namun, pendekatan institusional semata juga tidak cukup. Demokrasi tidak hanya mengatur bagaimana parlemen bekerja, tetapi juga bagaimana kehendak rakyat diterjemahkan secara jujur. Karena itu, jalan tengah perlu dirumuskan dengan lebih cermat dan terukur.
Itu artinya, jika kemudian fraksi gabungan hendak menjadi opsi atau pilihan, maka
pengelompokannya seharusnya berbasis pada rumpun ideologi, platform kebijakan, atau visi politik yang relatif sama atau sejalan.
Dalam konteks ini, bila ada diantara partai-partai kecil yang ketika disatukan ada yang tidak dalam irisan ideologi atau platform kebijakan dan visi politik yang sama, partai atau kursi parlemennya boleh bergabung dengan fraksi partai besar sebangun atau sejalan garis ideologinya.
Model ini lebih sejalan dengan konsep programmatic party system, di mana partai dan fraksi dibangun atas kesamaan gagasan, bukan sekadar kedekatan aritmetika kursi.
Dengan demikian, suara pemilih tidak sekadar “diselamatkan”, tetapi juga dijaga maknanya. Pemilih partai kecil tetap diwakili oleh fraksi yang memiliki orientasi politik yang dapat dikenali dan dipertanggungjawabkan secara politik dan moral.
Dalam format ini perdebatan tentang ambang batas parlemen bukan semata soal desain teknis pemilu, melainkan tentang kualitas demokrasi itu sendiri.
Menyelamatkan suara rakyat adalah keharusan moral dalam demokrasi. Namun,
menyelamatkannya dengan cara yang mengaburkan ideologi dan arah politik justru berisiko menciptakan parlemen yang ramai secara jumlah, tetapi rapuh secara substansi.
Di titik inilah negara diuji: apakah akan sekadar mengelola angka, atau sungguh-sungguh merawat representasi. Demokrasi yang matang menuntut keduanya—suara rakyat yang tidak hilang, dan politik yang tetap berakar pada gagasan yang kuat.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain