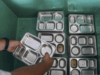Mengembangkan Budaya Berdemokrasi
Dengan menjangkarkan demokrasi pada kebudayaan dan kepribadian nasional tidaklah berarti bahwa pemuliaan terhadap nilai dan asas lama itu harus dilakukan dengan “mata tertutup”. Sedari awal, para pendiri Republik menyadari sepenuhnya adanya warisan tradisi lokal yang menindas. Untuk itu, diperlukan “mata terbuka” untuk melakukan peminjaman budaya secara selektif dengan keyakinan bahwa tradisi lama bisa diolah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kemanusiaan dengan mengambil faedah dari unsur-unsur budaya luar yang konstruktif.
Dalam ungkapan Ki Hadjar Dewantoro dikatakan: Dalam pada itu hendaknyalah kebudayaan lama disaring seperlunya; apa yang bertentangan dengan zaman baru dan/atau tak bermanfaat lagi harus dihapuskan, dihentikan atau dibekukan, sedangkan yang masih berguna diperbaiki. Jangan lupa memasukkan bahan baru, baik dari dunia luar maupun dari hidup baru sendiri, asalkan dapat mengembangkan dan memperkaya (Dewantoro, 1941; Reeve, 2013: 14).
Dalam lapangan politik, salah satu warisan tradisi lama yang menindas itu bernama feodalisme. Dalam kaitan ini, dasar ontologis menjadi Indonesia, selain merupakan perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme dari luar, juga merupakan perlawanan abadi terhadap feodalisme dari dalam. Elemen-elemen kultural untuk melakukan perlawanan terhadap feodalisme itu diramu dari unsur-unsur tradisi musyawarah demokrasi desa, tradisi egalitarianisme Islam, dan tradisi “sosial-demokrasi” yang diadopsi dari Barat.
Tradisi kekuasaan pra-Indonesia memang kerajaan feodal, yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu telah berkembang dalam budaya nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Tan Malaka, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya, pada abad 14 sampai 16 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal di masa itu bahwa “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Dengan demikian, menurutnya, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan dan patut-lah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak bila bertentangan dengan pikiran akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Tan Malaka, 2005:15-16).
Menurut analisis Hatta, demokrasi asli Nusantara itu dapat terus bertahan di bawah feodalisme karena, di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang terpenting bukanlah kepunyaan raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama atas tanah desa ini, maka hasrat tiap-tiap orang untuk memanfaatkan tanah ini harus mendapatkan persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong-royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang merembet pada urusan-urusan lainnya, termasuk mengenai hal-hal pribadi seperti mendirikan rumah.
Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum, yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: “Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” (Bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah-mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu.
Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, demokrasi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tak dapat dilenyapkan; bahkan tumbuh hidup sebagai adat istiadat. Hal ini, menurutnya, menanamkan keyakinan di lingkungan pergerakan kebangsaan “bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya”, seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau, “indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan”; tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1960: 121-123).
Hatta menambahkan dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli di Nusantara. “Yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana.” Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi yang damai. Tidak sering rakyat yang sabar berbuat seperti itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempetimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hak menyingkir, dapat dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri (Hatta, 1960: 123).
Tradisi demokrasi desa itu diperkuat oleh nilai-nilai demokratis dari Islam. Tentang kontribusi Islam, Bung Karno menyebutkan bahwa tradisi Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis (Soekarno, 1965: 265). Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.
Nilai-nilai demokratis Islam itu bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tawhid, Monotheisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tawhid. Kelanjutan logis dari prinsip Tawhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat serta pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Madjid, 1992: 4).
Kehadiran Islam di Nusantara membawa perubahan penting dalam pandangan dunia (world view) dan etos masyarakat, terutama, pada mulanya, bagi masyarakat wilayah pesisir. Menurut Dennis Lombar, Islam meratakan jalan bagi modernitas dengan memunculkan masyarakat perkotaan dengan konsepsi ‘kesetaraan’ dalam hubungan antarmanusia, konsepsi ‘pribadi’ (nafs, personne) yang mengarah pada pertanggungjawaban individu, serta konsepsi waktu (sejarah) yang ‘linear’, menggantikan konsepsi sejarah yang melingkar (Lombard, 1996: II, 149-242). Dalam pandangan Lombard, pengaruh modernisasi dan nilai-nilai humanisme Barat pada dasarnya melanjutkan jalan yang sebelumnya telah diratakan oleh pengaruh Islam.
Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter (Wertheim 1956: 205). Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam Dunia Melayu berkembang peribahasa, “Melayu pantang membantah.” Lewat pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi, “Raja adil, raja disembah’ raja zalim, raja disanggah.” Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhap sistem “kasta” baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial (Wertheim, 1956: 205).