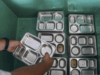Jakarta, Aktual.com – Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa hari silam mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,02%. Angka ini lebih tinggi ketimbang 2015 yang dikoreksi, yaitu 4,88%. Dibandingkan pertumbuhan negara-negara maju yang tergabung di G-20, kinerja ini jelas lebih tinggi. Maklum, pertumbuhan ekonomi negara maju sudah mentok. Mereka bergerak sangat lambat, rata-rata hanya 1-2%.
Tapi, dibandingkan Cina dan India, kita jelas kalah telak. Cina yang pada triwulan pertama 2016 saja mampu tumbuh di 6,7%. Sebelummya selama belasan tahun, ekonomi Negeri Tirai Bambu ini terbang belasan persen. Sedangkan India terbang lebih tinggi lagi, yaitu di posisi 7,3%. Bahkan Indonesia juga keok saat harus berhadapan dengan Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Ekonomi mereka mampu terkerek ke posisi di atas 6%.
Pertanyaannya, apakah kita puas dengan pertumbuhan yang berkisar di angka 5%? Kalau saya jadi Presiden Jokowi, tentu jawabnya tidak. Dengan hanya bermodal 5%, sulit bagi saya untuk maju Pilpres pada 2019 kelak. Pasalnya, 5% adalah angka yang biasa-biasa saja. Bahkan, maaf, dibandingkan era Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang pernah nangkring di 6%, jelas kinerja tersebut bisa disebut ‘belum ada apa-apanya’.
Fakta ini mestinya mampu memaksa Jokowi untuk melecut tim ekonominya agar Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Paling tidak, tahun depan mencapai 6%. Kalau target ini bisa digapai, pada 2019 mungkin bisa dikerek lagi menjadi 7%. Nah, dengan ekonomi yang naik di kisaran angka tersebut, Jokowi boleh merasa pe-de untuk ikut berlaga dan memenangi Pilpres 2019.
Ekspansi, bukan kontraksi
Untuk itu, ada sejumlah langkah yang mau tidak mau harus ditempuh untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di tengah masih lesunya perekonimian global. Dalam satu tarikan nafas, pemerintah perlu mengambil langah counter cyclical policies. Yaitu, kebijakan fiskal yang pada intinya meningkatkan pengeluaran (ekspansi) dan memotong pajak selama resesi.
Negara-negara besar seperti Amerika, Jepang, dan Cina biasanya memompa ekonominya dengan kebijakan fiskal dan moneter. Amerika bahkan tidak segan-segan mencetak uang banyak-banyak untuk memompa ekonomi domestiknya (dan internasional). Masih ingat kebijakan quantitative easing/QE-nya Amerika? The Fed rajin belanja obligasi pemerintah, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan pasokan uang. Kabarnya, sejak 2008, sekitar US$4 triliun digelontorkan ke pasar. Hasilnya, mantap. AS berhasil keluar dari krisis pada 2009. Lalu secara bertahap Negeri Paman Sam itu mulai menerapkan tapering policy, karena dianggap ekonomi sudah mulai pulih.
Sebaliknya Indonesia, biasanya malah melakukan kontraksi habis-habisan. Inilah yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani yang menggunting anggaran hingga Rp73 triliun tahun silam. Cara lain yang biasa dilakukan adalah mencari utangan sebesar-besarnya, mengobral BUMN strategis, dan menaikkan berbagai harga kebutuhan dasar rakyat. Listrik, BBM, gas, dan lainnya. Jelas ini kebijakan yang bukan saja tidak kreatif, tapi juga malas!
Kebijakan terobosan
Kalau mau, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan tim ekonomi Jokowi untuk memompa perekonomian. Lewat jalur fiskal misalnya, lakukan revaluasi asset secara lebih massif. Tahun silam, revaluasi aset telah menggelembungkan aset BUMN lebih dari Rp800 triliun. Pajak yang berhasil ditangguk mencapai Rp32 triliun. Jika dikombinasi dengan sekuritisasi asset, maka bukan mustahil kita bakal meraup dana lagi sekitar US$10 miliar.
Selain itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga bisa mengomandoi timnya untuk mendongkrak daya beli rakyat. Tentu saja, caranya tidak dengan menggelontor duit ke pasar. Ini sama saja bunuh diri. Inflasi akan terbang tinggi ke langit.
Ada cara mudah dan murah, yaitu menggusur kebijakan kuota impor dan menggantinya dengan sistem tarif. Sistem kuota inilah yang telah melahirkan para begal komoditas pangan yang tergabung dalam berbagai kartel. Mereka dengan seenak perutnya melambungkan harga, sehingga rakyat harus membayar lebih mahal daripada semestinya.
Dari sisi moneter, pemerintah harus memacu kredit. Dengan laju kredit yang cuma 7%, jelas sangat tidak memadai. Kalau bisa digenjot rata-rata nasional minimal jadi 15%, mungkin ekonomi bisa menggeliat dan bergairah lagi. Tapi, perbankan tentu saja harus tetap prudent. Mengobral kredit secara serampangan sama saja mengundang hantu non-performing loan (NPL) yang amat mengerikan.
Sedangkan dari sisi kebijakan, pemerintah dituntut kreatif. Harus berani membuat terobosan-terobosan, jangan melulu terkungkung pada buku-buku teks sekolahan. Dulu, tahun 2000an, Menko Perkonomian Rizal Ramli, misalnya, membuka izin maskapai penerbangan. Dampaknya, biaya terbang/km turun hingga 60%. Jumlah penumpang melonjak hingga 500%. Angka ini bahkan melampaui rekor tertinggi sebelum krismon menghempas pada 1998.
Sektor lain yang menunggu kebijakan terobosan pemerintah antara lain pariwisata. Jika digarap dengan benar, target mencapai 20 juta wisman dan devisa US$20 miliar sampai 2019 bukan lah ilusi.
Namun pertanyaan pentingnya kini adalah, siapkah tim ekonomi Jokowi mengeksekusinya? Atau, pertanyaan yang lebih pas lagi adalah, maukah (dengan huruf tebal) mereka melakukannya? Pasalnya, dengan melihat rekam jejak Sri Mulyani, Darmin, dan anggota tim lainnya, rasa-rasanya hampir pasti mereka tidak mau. Orang-orang ini sudah teramat lama terjebak pada school of thinking. Apa-apa yang tidak diterima dari sekolahan (Barkeley dan para gengnya), pasti bakal ditolak. Mereka adalah para pejuang dan penganut mazhab neolib yang gigih dan pantang menyerah!
Kebijakan Sri yang memangkas anggaran, misalnya, adalah bukti nyata bagaimana dia bagitu setia dengan kacamata kuda neolibnya. Padahal, pemotongan anggaran hanya bagus di mata internasional (baca: World Bank ,IMF dan para konconya). Kenapa? Karena dengan memotong anggaran nilai aset di dalam negeri bakal stagnan, bahkan bisa turun. Nah saat itulah investor getol belanja aset di sini.
Pemotongan anggaran juga memberikan ruang lebih luas kepada APBN. Kelonggaran ini dimanfaatkan untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri. Tentu saja, para bond holder bersorak-sorai karenanya. Lihat saja, berapa alokasi duit yang disiapkan untuk membayar utang di APBN 2016 dan 2017. Pada APBN 2017, ada Rp221 triliun! Dahsyat kan? Sisanya untuk membiayai belanja rutin pemerintah yang terus saja menggembung. Padahal untuk itu, rakyat diperas dengan kenaikan harga berbagai barang dan jasa kebutuhan dasar serta pajak yang kian mencekik.
Seperti masih dianggap kurang, pemerintah justru tampak kalap, dengan memajaki segala apa saja. Prilaku panik inilah yang kemudian melahirkan pomeo, di negeri ini cuma, maaf, kentut dan meludah, yang tidak kena pajak. Pajak kendaraan bermotor yang didongkrak hingga 300% adalah salah satu contoh betapa paniknya pemerintah. Akibatnya, beban rakyat yang sudah berat, jadi kian berat saja.
Sri sendiri mengakui kondisi APBN 2017 tidak sehat. Kita berutang untuk membayar bunga utang. Ini karena terjadi defisit keseimbangan primer senilai Rp111,4 triliun. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer defisit, artinya pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.
Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi. Gawat, kan?
So, apa yang harus Jokowi lakukan? Pecut tim ekonomi agar mau bekerja secara cerdas, tepat, dan cepat. Jangan puas dengan ekonomi yang hanya 5% atau lebih sedikit. Maksud saya, itu kalau Jokowi mau melenggang ke Pilpres 2019 dengan modal yang cukup. Maklum, modal Presiden yang mantan Walikota Solo itu kini nyaris ludes karena kasus si mulut jamban Ahok. Nah… (*)
Ditulis Oleh: Edy Mulyadi,
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka