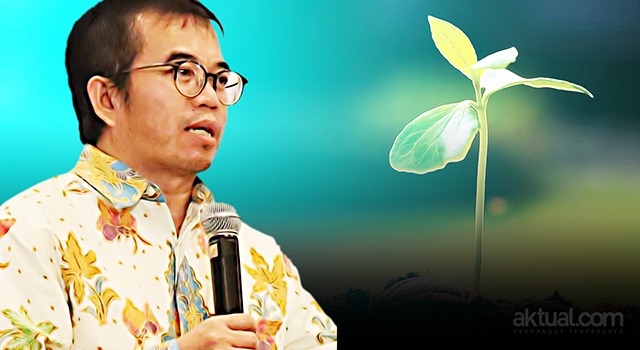Jakarta, Aktual.com – Saudaraku, cara mencari Tuhan dengan tegak lurus di jalan-Nya adalah trayek yang dilalui Wahid Hasjim. Ia tumbuh dalam lingkungan religius dan sejak kecil menunjukkan ketertarikan pada masalah-masalah keagamaan; lantas memperdalam ilmu-ilmu keagamaan dan berakhir sebagai pemimpin (tokoh) keagamaan.
Ia adalah “putra dari Bapaknya”, Hadrat-al-syeikh K.H. Hasjim Asj’ari, pendiri Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Pesantren yang terkenal sebagai pusat teladan dari modernisasi komunitas epistemik Islam tradisionalis.
Didirikan pada 1899, pesantren ini pada mulanya cenderung rejektif terhadap pengaruh modernitas dengan memilih strategi otentisasi berbasis tradisi lokal. Selama hampir dua puluh tahun pertama sejak pendiriannya, pesantren ini mempertahankan metode-metode pengajaran tradisional seperti sorogan dan wetonan.
Pada 1916, Kiai Ma’sum (anak menantu pertama Kiai Asj’ari yang pernah belajar di Makkah) memperkenalkan sistem pendidikan madrasah di lingkungan pesantren, yang kelak pada 1919 dikenal sebagai madrasah “Salafiyah Syafi’iyah”. Sejak didirikan, madrasah ini telah mengadopsi sistem kelas berjenjang dan pengajaran dalam kelas. Namun, baru pada 1919, pelajaran-pelajaran umum mulai bisa diajarkan karena adanya resistensi yang kuat di dalam pesantren terhadap apa pun yang berbau modern (Dhofier, 1982: 104).
Upaya lebih jauh untuk memodernisasi madrasah ini dilakukan oleh Mohammad Iljas (lahir 1911, anak dari kakak perempuan istri Asj’ari). Latar belakang pendidikannya sungguh tak lazim untuk kalangan Muslim tradisional. Dia belajar di HIS di Surabaya (1918-1925), kemudian setelah menyelesaikan pendidikan modernnya ini, dia memilih untuk memperdalam pengetahuan keagamaan di Pesantren Tebuireng. Pada 1929, dia diangkat sebagai lurah di pesantren itu dan menjadi kepala sekolah madrasah “Salafiyah Syafi’iyah”. Di bawah kebijakannya, kurikulum madrasah tersebut memberikan lebih banyak penekanan terhadap pengajaran ilmu alat (bahasa Arab) dan yang lebih penting, mulai memperkenalkan pelajaran-pelajaran umum dan meningkatkan pengetahuan umum para siswa dengan memperkenalkan koran, majalah, dan buku-buku yang ditulis dalam huruf Latin (Soekadri, 1979: 56).
Kebijakan modernisasi ini dilanjutkan oleh sang “Putra Mahkota”, Abdul Wahid Hasjim (1913-1953). Awalnya dia belajar di pesantren ayahnya dan pesantren-pesantren yang lain. Selain itu, ia juga belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris secara autodidak, serta membaca koran dan majalah baik yang ditulis dengan huruf Arab maupun huruf Latin, sebelum kemudian menghabiskan waktu setahun untuk belajar di Makkah (1932-1933).
Saat kembali, dia mendirikan sebuah madrasah modern dalam lingkungan pesantren ayahnya yang diberi nama madrasah “Nidhomiyah”. Sekitar 70% dari kurikulum madrasah ini dicurahkan pada pelajaran-pelajaran umum, seperti bahasa Belanda dan bahasa Inggris, selain juga bahasa Arab. Selain itu, dia mulai mendirikan sebuah perpustakaan yang berlangganan berbagai koran dan majalah, terutama yang ditulis dengan huruf Latin. Pelajaran-pelajaran berpidato dalam bahasa Belanda dan Inggris, serta mengetik juga mulai diperkenalkan kepada para siswa (Dhofier, 1982: 106; Soekadri, 1979: 57).
Dengan ilmu keagamaan yang mendalam, serta wawasan pengetahuan umum yang relatif luas, Wahid Hasjim tampil sebagai ulama-intelek, yang memberinya modal sosial untuk tampil sebagai pemimpin muda yang meroket saat pendudukan Jepang. Dengan politik Jepang yang pada mulanya mencoba menarik simpati komunitas Islam pedesaan, posisi K.H. Hasjim Asj’ari sebagai pemimpin kharismatis secara fungsional praktis dijalankan oleh Wachid Hasjim.
Selama masa pendudukan Jepang, kendatipun Jepang berusaha untuk “mendekati” tokoh-tokoh Islam, Wahid Hasjim memperlihatkan dirinya sebagai sosok pemimpin Islam berintegritas yang “tak dapat dijepangkan”.
Cerminan keberaniannya terlihat dalam kisah perjalanan naik kereta dari Stasiun Kroya menuju Jakarta menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti yang diceritakan kembali oleh Saifuddin Zuhri:
“Sudah beberapa hari saya dalam perjalanan bersama Alm. K.H.A. Wahid Hasjim. Kereta-api malam berhenti agak lama di stasiun Banjarpatoman dekat Tasikmalaya. Sudah hampir jam setengah empat malam, padahal kami belum menyediakan sahur. Ketika itu sudah masuk bulan Ramadhan, menjelang bulan Agustus 1945. Dengan melalui penumpang-penumpang yang sangat padat bergelimpangan tidur di bordes, saya turun sebentar di peron stasiun untuk membeli apa akan saya beli; sudah kedahuluan dibeli orang lain yang barangkali perlu buat sahur, sehingga saya hanya berhasil memperoleh 4 butir telor ayam rebus. Ah lumayan juga buat sahur! Waktu akan dimakan dengat niat untuk sahur puasa wajib, Alm. K.H.A. Wahid Hasjim menanyakan mana air buat minum? Karena saya tidak berhasil memperoleh air minum, maka sambil kelakar saya menjawab: ‘Zonder minuman tak apa, toh besok pagi kita haus juga…!
….Sejak kami naik di stasiun Kroya, 3 orang opsir Jepang yang duduk bersama kami di kelas I itu senantiasa mengawasi gerak-gerik kami dengan pandangan mencemoohkan. Pada waktu kami memerlukan air minum buat sahur, mereka mengejek-ejek, seorang di antaranya membuang air tehnya yang masih panas dari persediaan termosnya. Itu waktu saya sudah mulai naik darah, tetapi Alm. K.H.A. Wahid Hasjim menenangkan hati saya sambil menasehati bahwa janganlah kita ributkan perkara kecil itu. Nanti akan datang saatnya kita membikin perhitungan dengan mereka secara besar-besaran dalam masalah yang besar, katanya sambil mengulang-ulang sabar, sabar!
Rupanya Jepang-Jepang itu tidak senang ada ‘genyuming-genyuming’ seperti kami berdua duduk di kelas I menyamai mereka, padahal seharusnya mereka tahu bahwa orang yang bisa duduk di kelas I menyamai mereka, padahal seharusnya mereka tahu bahwa orang yang duduk di kelas I di waktu itu bukanlah ‘genyuming’ sembarangan…! Caranya mencemoohkan kami diteruskan lagi yaitu ketika Alm. K.H.A. Wahid Hasjim hendak mengembangkan baju mantelnya buat sajadah ketika kami hendak sembahyang Subuh di peron stasiun Cibatu; salah seorang opsir Jepang tadi meludah di lantai yang akan kami gunakan untuk sembahyang. Hati saya bertambah panas, tapi Alm. K.H.A. Wahid Hasjim tetap tenang dan berkata bahwa peristiwa itu belum saatnya untuk memuntahkan amarah, katanya. Akan tetapi setelah terjadinya ‘peristiwa jendela’ rupanya beliau tidak bisa menjadi orang sabar terus-menerus. Peristiwa-jendela itu duduknya perkara demikian:
Kami berdua duduk bersanding menghadap arah jalannya kereta-api. Kereta-api yang berjalan di lereng-lereng pegunungan di daerah Priangan itu menyebabkan lokomotif mengeluarkan tenaga maksimalnya sehingga menyebabkan banyak menghamburkan abu dan api, memasuki tempat duduk. Karena abu dan api itu langsung mengenai kami berdua, maka Alm. K.H.A. Wahid Hasjim lalu menutup jendela di samping kami. Melihat itu tiba-tiba dari mulut salah seorang Jepang yang duduk di muka kami itu keluar perkataan: ‘Kurang ajar, bakero!’ Almarhum menjawab kontan: ‘Tuan yang kurang ajar!’, ‘Ojo berani sama Nippon!’, kata Jepang itu. Tapi dengan cepat tangan almarhum memegang pedang samurai kepunyaan Jepang itu hendak direbutnya jikalau tidak dihalang-halangi oleh Jepang-Jepang yang lain. Suasana dalam kereta-api kelas I sudah hampir panik, akan tetapi tiba-tiba salah seorang Jepang yang lain segera mendekati kami sambil senyum kecut dengan katanya: ‘Kami minta maaf kepada Tuan, maaf maaf!’, sambil tangannya menahan tangan almarhum. Dengan sikap menguasai dirinya K.H.A. Wahid Hasjim berkata: ‘Tuan harus tahu, peristiwa ini akan saya bikin panjang, menjadi peristiwa antara bangsa dengan bangsa!’ Saya tidak tahu, apakah Jepang-Jepang itu mengerti arti perkataan yang tajam itu. Tetapi saya yakin, bahwa jiwa daripada kalimat-kalimat gagah yang dikeluarkan dengan penuh kesadaran dari jiwa yang besar tentu akan mempunyai dasar dan bekas yang sangat kuat. Entah karena akibat insiden itu atau memang menurut rencana, maka pada waktu kereta-api tiba di stasiun Bandung, Jepang-Jepang itu turun semua. Sambil mataku mengikuti langkah-langkah Jepang yang hendak meninggalkan kereta kita, dari mulut saya melompat kata-kata: ‘Rupanya Jepang-Jepang ini sedang menghadapi sekaratnya!’ Dengan muka geram, K.H.A. Wahid Hasjim menyambung: ‘Setan gundul’ sedang sekarat, tindakannya semangkin gila! Istilah ‘setan gundul’ atau ‘syayatin’ biasa digunakan beliau untuk mengganti nama Jepang yang sedang berkuasa di negeri kita di waktu itu (Aboebakar, 2011: 202-205).
Begitulah sosok Wahid Hasjim: teguh dalam pendirian, namun tetap mengembangkan semangat persaudaraan melintasi batas-batas ideologi dan agama.
Tak heran, menjelang dan selama revolusi kemerdekaan, ia tampil sebagai sosok pemimpin muda Islam dengan peran kepemimpinan yang menonjol. Sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), ia terpilih sebagai anggota tim kecil panitia delapan bentukan resmi BPUPK; Ia juga menjadi anggota tim kecil Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta. Setelah itu, ia juga terlipih sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai pemimpin Islam, semasa kontestasi ideologi yang sengit, wajar saja bila beliau memiliki agenda keislaman. Yang membuatnya istimewa, posisi pendapatnya masih bisa menerima argumentasi yang berbeda dalam proses permusyawaratan. Sekali mufakat dicapai, beliau komit pada kesepakatan bersama: mendukung negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan.
Wahid Hasjim punya andil besar dalam usaha perwujudan negara Indonesia sebagai negara religius yang inklusif; dengan “menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Setelah kemerdekaan, beliau terpandang sebagai tokoh Islam yang pernah memimpin kementerian agama dengan pergaulan yang luas dan luwes. Tokoh muda NU ini bisa berdiskusi berjam-jam sampai larut malam dengan orang yang disapa “Paman Husein” yang tak lain adalah Tan Malaka yang berhaluan kiri. Wachid Hasjim menghormati Tan Malaka, dan begitu juga sebaliknya. Perdebaan pandangan politik tidak membuat keduanya saling menjauh tetapi saling menghargai. “Sepanjang dia tidak mengganggu, tidak ada salahnya kita menjalin hubungan baik,” begitu dinyatakan Gus Dur mengutip ayahnya.
Wahid Hasjim juga mengembangkan sikap toleransi yang positif dengan proaktif menjalin pergaulan lintas aliran, lintas ideologis. Seperti dikisahkan oleh anaknya yang lain, Salahuddin Wahid, bahwa ayahnya sering mengajak anak-anak berkunjung ke rumah Soebardjo, atau menyambangi tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmita. Lebih dari itu, Wahid Hasjim juga rajin berkunjung ke rumah tokoh yang berbeda paham, misalnya Mohammad Yamin dan Mr. Sartono dari Partai Nasional Indonesia. Menurut Salahuddin, “Bapak hendak menunjukkan kepada kami, ia tidak pernah membeda-bedakan orang” (Tempo, 2011: 32).
Dalam mengembangkan sikap saling menghargai, Kiai Hasjim bisa menentukan secara dewasa kapan bisa berbeda, kapan bisa tetap bersaudara. Urusan politik tidak dicampuradukkan dengan urusan (hubungan pribadi). Beliau pernah menegur istrinya, Solehah, karena menolak memberi tumpangan kepada seorang anggota Konstituante yang menyudutkan Kiai Hasjim dalam sidang. Dengan jernih pak Kiai mengingatkan istrinya, “Urusan pekerjaan dan pribadi tak bisa dicampur-aduk,” ujarnya (Tempo, 2011: 58-59).
Terhadap sesama tokoh Muslim sendiri, ia memperlihatkan semangat saling menghargai dan menghormati dengan memanjangkan tali silaturahim. Seusai shalat jumat di Masjid Matraman, Bung Hatta dan A. Wahid Hasjim biasa berbincang-bincang (Barton, 2012: 37). Wahid Hasjim yang NU, pada masa revolusi fisik menjadi penasihat pribadi Panglima Besar Soedirman yang tokoh Muhammadiyah. Bahkan Gus Dur, putra sulung Wahid Hasjim, ketika sekolah di Yogyakarta dititipkan pada tokoh Muhammadiyah, K.H. Juneidi yang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Gus Wahid meninggal dalam usia yang relatif pendek (40 tahun), namun meninggalkan keteladanan yang panjang; jadi role model bagi generasi penerusnya: berislam yang kuat namun penuh welas asih, dengan menghargai dan melindungi yang berbeda.
(Yudi Latif, Makrifat Pagi)