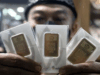Negara ini memiliki refleks hukum yang sangat terlatih, terutama ketika berhadapan dengan rakyat kecil. Pada 2009, Nenek Minah, warga Banyumas, diseret ke pengadilan karena memetik tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Pengadilan menyatakan ia bersalah, sebuah putusan yang kemudian menjadi simbol ketimpangan penegakan hukum di Indonesia (Kompas, 2009; Tempo, 2009).
Beberapa tahun kemudian, pola serupa terulang. Pada 2014–2015, Nenek Asyani di Situbondo ditahan dan diadili karena dituduh mencuri kayu jati milik Perhutani, meski ia bersikeras kayu itu berasal dari lahannya sendiri. Ia baru divonis bebas setelah tekanan publik menguat (Kompas, 2015; BBC Indonesia, 2015).
Dalam dua kasus itu, hukum bekerja cepat, prosedural, dan tanpa ragu. Negara hadir penuh wibawa di hadapan perempuan-perempuan lansia dengan daya tawar nyaris nol.
Namun refleks itu mendadak melemah ketika yang runtuh bukan satu batang pohon, melainkan jutaan hektare hutan, dan yang hanyut bukan beberapa barang, melainkan ribuan nyawa manusia.
SOROTAN: Ketika Pelayanan Publik Menunggu, Izin Eksploitasi Melaju
Hingga 14 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.006 orang meninggal dunia, sekitar 217 orang masih hilang, dan lebih dari 624 ribu warga mengungsi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (BNPB, 2025; DetikNews, 2025).
Tragedi ini bukan semata akibat hujan ekstrem. Berbagai laporan media dan kajian lingkungan menunjukkan bahwa bencana tersebut terjadi di atas bentang alam yang telah lama dilemahkan oleh pembalakan hutan, konsesi tambang, dan alih fungsi lahan di kawasan hulu daerah aliran sungai (Mongabay Indonesia, 2025).
WALHI mencatat bahwa sepanjang 2016–2024, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare hutan akibat aktivitas ratusan perusahaan di sektor tambang, sawit, dan konsesi kehutanan (WALHI, 2025).
Di Sumatera Barat, kehilangan hutan primer sejak awal 2000-an mencapai sekitar 320 ribu hektare, dengan total kehilangan tutupan pohon—primer dan sekunder—mendekati 740 ribu hektare (WALHI Sumbar, 2024). Data ini menunjukkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga air dan pelindung alami dari banjir serta longsor.
SOROTAN: Ekosistem Dirusak Cepat, Solidaritas Dipalang Administrasi
Dalam perspektif kriminologi lingkungan dan bencana, peristiwa semacam ini tidak lagi dipahami sebagai bencana alam murni. Banjir dan longsor dipandang sebagai akumulasi keputusan manusia: izin yang diterbitkan, pengawasan yang dilemahkan, serta pembiaran negara terhadap kerusakan lingkungan yang telah diketahui risikonya (White, 2011; South, 2014). Dengan kata lain, air bah hanyalah fase akhir dari rangkaian kebijakan yang bermasalah.
Ironinya, hukum justru kehilangan ketajamannya ketika pelaku berada di level struktural. Ombudsman Republik Indonesia mencatat bahwa perubahan kewenangan perizinan pertambangan dari daerah ke pusat menciptakan kompleksitas tata kelola dan meningkatnya maladministrasi, tanpa menghentikan laju konsesi (Ombudsman RI, 2021).
Dokumen menumpuk, legal opinion berlarut, tetapi izin tetap berjalan. Tidak ada sidang cepat, tidak ada vonis simbolik, apalagi efek jera.
Kontrasnya nyaris kejam. Nenek memungut kayu: kriminal. Korporasi menggunduli hutan: investasi.
SOROTAN: Banjir Sumatera dan Korupsi Ekologis di Meja Negara
Dalam bahasa kriminologi, situasi ini dikenal sebagai kejahatan karena pembiaran (crimes of omission). Kerusakan dan korban muncul bukan karena satu tindakan ilegal tunggal, melainkan karena negara mengetahui risikonya namun gagal bertindak (White, 2018; South & Brisman, 2013).
Kejahatan semacam ini sering luput dari jerat hukum formal karena korbannya tersebar, muncul belakangan, dan pelakunya berlapis-lapis.
Ketika bencana datang, negara justru sibuk berdebat soal prosedur; kewenangan, regulasi, dan administrasi bantuan. Donasi dipersoalkan izinnya, relawan diingatkan aturan, dan penyaluran bantuan berjalan lamban di bawah bayang-bayang birokrasi.
Seolah-olah banjir bandang bisa dihentikan dengan rapat koordinasi, dan longsor dicegah dengan surat edaran. Padahal akar persoalannya telah lama diketahui, yaitu kerusakan ekologis yang dilegalkan dan dibiarkan.
SOROTAN: Sumatera Banjir Bandang, Jakarta Banjir Alasan
Jika hukum benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kehidupan, maka refleks tercepatnya seharusnya diarahkan pada sumber petaka, bukan pada korban paling lemah.
Selama negara lebih cepat mengadili Nenek Minah dan Nenek Asyani dibanding menindak pembalakan hutan yang memproduksi bencana, setiap banjir di Sumatera bukan sekadar musibah alam. Ia adalah konsekuensi kebijakan dan putusan sunyi atas kegagalan keberpihakan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto