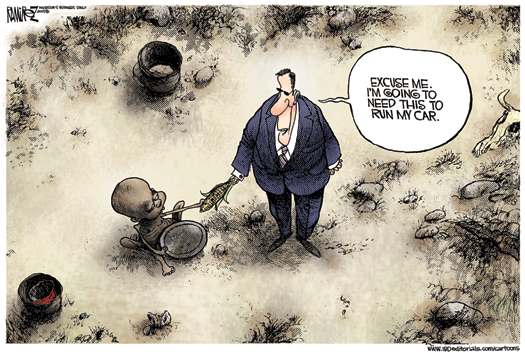Jakarta, Aktual.com — Indonesia memiliki potensi biofuel (bahan bakar nabati) terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Ketika potensi bahan bakar fosil global menipis, potensi biofuel menempati tempat penting dalam perang energi global.
Sejak rezim SBY, negara ini sudah merencanakan dan bahkan membangun industri biofuel di Indonesia bagian Timur. Pembangunan pabrik biodiesel di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dalam skala besar adalah salah satu contohnya. Bahkan ke depan, akan dibangun juga infrastruktur distribusi dan transportasi-nya untuk mendukung produksi dan penyediaan bahan bakunya.
Memang harus diakui pasar energi terbarukan global semakin lama semakin menjanjikan. Sebuah lembaga riset, Pike Research bahkan memperkirakan pasarnya akan meningkat meningkat dua kali lipat satu dekade mendatang.
Dalam laporan risetnya “Biofuels Markets and Technologies”, Pike Research menyebut permintaan biofuel global akan mengalami kenaikan dari 71,8 miliar galon per tahun saat menjadi lebih dari 1 triliun galon per tahun pada 2021.Atau naik dari USD 82,7 miliar per tahun pada 2012 menjadi USD 185,3 miliar per tahun 2021. Ini bisnis yang sangat menggiurkan.
Pike Research juga mencatat, sampai tahun 2012 saja produksi biofuel global dunia hanya mencapai 29,4 miliar galon per tahun dan akan meningkat hingga 49,5 miliar galon per tahun pada 2021. Jadi masih sangat besar jurang permintaan dan kemampuan produksi biofuel global. Saat ini AS masih jadi pemimpin pasar biofuel dimana sekitar 70 persen pasar dikuasainya dengan memanfaatkan bahan dasar minyak jagung atau kedelai.
“Tingginya skala kebutuhan biofuel akan mengubah peta industri dan geopolitik secara radikal,” kata analis senior Pike, Mackinnon Lawrence seperti dikutip dari sebuah media online nasional.
Jadi tak salah kalau Indonesia (dan Malaysia) dengan potensi sawit terbesar di dunia saat ini jadi rebutan banyak negara untuk ‘menguasai’ pasar biofuel global. Apalagi Indonesia bukan hanya memiliki sawit. Banyak bahan dasar lain yang cukup melimpah di Indonesia seperti sawit, jarak dll.
World Bank dan Gallagher Review
Namun impian cerahnya bisnis masa depan biofuel tidak seperti yang dibayangkan banyak analis dan pengamat ketika melihat beberapa kenyataan dan realitas yang justru kontradiktif.
Juli 2008 lalu, peneliti geopolitik pangan global, F William Engdahl mengatakan bahwa World Bank sebenarnya telah merilis laporan penting soal gejolak harga pangan global. Report itu menyatakan bahwa kegiatan kultivasi di sekitar bisnis biofuel yang dilakukan di AS dan negara-negara Uni Eropa ternyata berpengaruh besar terhadap kenaikan harga dan pangan global yang cukup besar.
Engdahl mengatakan “The World Bank secret report says that at least 75% of the recent price rises are due to land being removed from agriculture—mainly maize in North America and rapeseed and corn in the EU—in order to grow crops to be burned for vehicle fuel”.
Karena laporan itu diangggap mengganggu industri biofuel AS, Presiden Bush menekan World Bank untuk tidak menyebarkan report tersebut. Namun Bush lupa, report itu ternyata sudah beredar di beberapa media dan beberapa LSM Internasional yang berkepentingan dengan pangan.
Apa sebenarnya inti dari laporan World Bank tersebut?
Laporan itu sempat beredar beberapa hari sebelum pertemuan penting negara G8 yakni 34th G8 Summit yang diselenggarakan di Hokkaido Jepang pada 7-9 Juli 2008 lalu. Indonesia hadir dalam pertemuan penting yang salah satu agendanya adalah membahas soal perubahan iklim dan harga pangan global.
Entah, apakah benar delegasi Indonesia sudah menerima salinan bocoran laporan World Bank itu atau tidak saat itu. Namun yang jelas dalam laporan itu dijelaskan bahwa meningkatnya harga pangan global sampai dua kali lipat dalam waktu 3 tahun terakhir (dari tahun 2005 sampai 2008) ternyata berkorelasi langsung dengan meningkatkan jumlah orang yang hidup di bawah tingkat garis kemiskinan. Mau tahu jumlahnya? Ada sekitar 100 juta orang miskin baru muncul, termasuk di Indonesia akibat harga pangan global naik. Mengerikan.
Laporan itu juga mencatat bahwa kenaikan harga pangan global mencapai 140% sejak 2002 sampai Februari 2008. Sekitar 15% kenaikan itu disumbang oleh meningkatnya harga energi dan pupuk. Sedangkan 75% disumbang oleh peningkatan produksi biofuel. Ingat, sampai saat ini sebagian besar pasar biofuel global diproduksi oleh beberapa perusahaan AS dan Uni Eropa.
Engdahl kemudian menekankan kembali peran industri biofuel dalam menciptakan krisis pangan global, “The study (World Bank Report.red) demonstrates that production of bio-fuels has distorted food markets in three main ways. First, it has diverted grain away from food for fuel, with over a third of US corn now used to produce ethanol and about half of vegetable oils in the EU going to production of bio-diesel. Second, farmers have been encouraged to set land aside for bio-fuel production. Third, it has sparked financial speculation in grains, driving prices up higher”.
Bukan hanya World Bank. Ternyata dampak industri biofuel juga diteliti oleh pemerintah Inggris. Sebuah lembaga bernama Renewable Fuels Agency (RFA) yang dibentuk pemerintah Inggris mengeluarkan sebuah laporan pada 7 Juli 2008, bertepatan dengan dimulainya G8 Summit ke 34 di Hokkaido. Report itu berjudul “The Gallagher Review of the Indirect Effects of Biofuels Production”.
Riset penting yang dipimpin oleh Professor Ed Gallagher itu menyatakan seperti ini, “…in the light of new evidence suggesting that an increasing demand for biofuels might indirectly cause carbon emissions because of land use change, and concerns that demand for biofuels may be driving food insecurity by causing food commodity price increases”. Mirip hasilnya dengan laporan World Bank tadi.
Akibat rekomendasi laporan ini, Inggris memutuskan untuk mengurangi laju pengembangan industri biofuel-nya. Bahkan Guardian melaporkan bahwa sejak Januari 2009 lalu kampanye nasional yang digelar pemerintah Inggris tentang ‘Biofuel sebagai energi alternatif berkelanjutan pengganti minyak bumi’ dihentikan karena biofuel dianggap berbahaya bagi ketahanan pangan negara Inggris.
Namun berdasarkan rilis yang dikeluarkan beberapa LSM, para pemimpin negara G8 saat itu tutup mulut ketika melihat fakta yang dirilis World Bank dan Gallagher Review itu. “Para pemimpin kelihatannya mengabaikan bukti kuat bahwa biofuel adalah faktor penting penyumbang krisis harga pangan global,” kata policy adviser Oxfam, Robert Bailey kepada Guardian beberapa waktu lalu.
Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia?
Ingat. Gara-gara AS mampu menguasai 70 persen pasar industri biofuel global saja maka harga jagung dan kedelai global naik hampir dua kali lipat. Petani jagung dan kedelai di AS lebih memilih menjual hasil panennya ke industri biofuel yang ada. Bukan lagi untuk mencukupi kebutuhan pangan.
Jadi ketika jagung dan kedelai mulai langka di pasar global maka harga kedua komiditi di pasar global juga naik. Efeknya, kenaikan dua komoditi tersebut memacu kenaikan harga komoditas pangan lainnya. Termasuk kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok di Indonesia beberapa tahun belakangan ini.
Layak jika AS dan Eropa berpikir keras untuk menjaga ketahanpangannya akibat meningkatnya pertumbuhan industri biofuel di sana. Nah, ketika melihat fakta bahwa sampai saat ini komoditas yang paling potensial (paling murah biaya produksinya) dan aman (tidak menggangu ketahanan pangan mereka) untuk dijadikan bahan baku biofuel adalah kelapa sawit maka mereka akan “memburu dan menjajah” lagi negara-negara penghasil sawit. Termasuk Indonesia dan Malaysia. Ini poin penting yang harus dipahami.
Apalagi, di Indonesia, selain kelapa sawit ada tebu, nipah, sagu dan beberapa tanaman dan buah yang juga dianggap potensial juga untuk menghasilkan biofuel. Indonesia sangat kaya dengan potensi bahan bakar nabati.
Jadi, jangan salah kalau AS dan Eropa melakukan cara apapun untuk menguasai industri sawit yang saat ini 85% produksi globalnya masih dikuasai Indonesia dan Malaysia.
Ambil contoh Wilmar International. Salah satu perusahaan terbesar di industri sawit Indonesia ini sudah punya teknologi pemrosesan kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati (bio diesel) buat pesawat jet. Perusahaan ini bahkan sudah membangun kilang pengolah (biorefinery) kernel sawit berkapasitas 500 ton per hari sejak Desember 2011 lalu. Alhasil, sekitar 20 persen bio-olefin dan 80 persen bio-diesel di Indonesia dihasilkan pabrik ini. Produk bio-olefin ini yang kemudian diolah menjadi bahan bakar pesawat jet.
Menurut Direktur Eksekutif Kawasan Industri Wilmar Gresik, Taufik Tamin beberapa waktu lalu, perusahaannya sengaja membeli teknologi pengolahan bahan bakar olefin untuk pesawat jet dari pemenang Nobel 2005, Robert H. Grubbs. Tak kurang sekitar Rp700 miliar uang dikeluarkan perusahaan ini untuk membeli teknologi tersebut. Dengan menggandeng investor, Elevance Renewable Sciences Inc., PT Wilmar yang basis bisnisnya bergerak di agribinis ini menancapkan langkah awal untuk memuluskan rencana bisnis kedepannya: biofuel.
Bahkan, pada 2015 ini Wilmar membentuk strategic partnership dengan Archer Daniels Midland Company (ADM) dalam hal: tropical oils refining di Eropa, global fertiliser purchasing, distribution, dan global ocean freight operations. Kedua perusahaan tersebut sepakat meluncurkan Olenex CV yang berkantor pusat di Rolle, Switzerland untuk me-handle penjualan dan marketing untuk seluruh produk minyak dan lemak nabati rafinasi ke seluruh Eropa dan Switzerland khususnya.
Itu belum catatan-catatan ekspansif beberapa perusahaan multinasional besar lain seperti Cargill Inc yang berkantor pusat di Minnetonka, Minnesota, AS. Atau Sinar Mas dan Asian Agri.
Intinya, agar ketahanan pangan AS dan Eropa tidak hancur akibat berkembangnya industri biofule maka industri yang ada di AS dan Eropa jangan lagi memakai jagung, kedelai dalam negerinya. Ambil saja kelapa sawit dari Indonesia dengan cara apapun, agar tetap murah.
Kalau bisa Indonesia dan Malaysia dicegah untuk bisa menghasilkan biofuel secara mandiri. Atau mencegah agar Indonesia dan Malaysia tak mampu mengembangkan industri produk-produk turunan kelapa sawit.
Kalau perlu, AS dan Eropa menempatkan banyak perusahaannya di Indonesia untuk menghasilkan biofuel. Indonesia cukup hanya menyediakan lahan dan bahan mentah saja. Dengan atas nama pemberdayaan petani sawit kecil, mereka memaksa pemerintah membuat aturan-aturan agar petani kecil dipermudah untuk membakar lahan, menanam sawit dan hasil mentahnya dijual ke mereka dan kemudian mereka olah menjadi biofuel.
Kalau ada industri sawit menengah milik pengusaha pribumi, atas nama keselamatan lingkungan, maka mereka menekan pemerintah untuk membuat UU agar tidak membuka lahan baru. Kalau terjadi kebakaran, maka pengusaha-pengusaha pribumilah yang jadi tersangkanya.
Mereka juga ingin, kalau perlu, sawah yang ada disulap untuk ditanami sorgum untuk menghasilkan biofuel (ini sudah terjadi.red). Kalau perlu juga seluruh ladang jagung, ladang tebu atau ladang-ladang yang ada hasilnya dijual ke perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia.
Atas nama investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah bahkan mempercepat perizinan untuk mengembangkan beberapa industri energi baru terbarukan di Indonesia. Dalam jangka pendek, naiknya tingkat investasi memang akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
Namun, kelak Indonesia mungkin akan menyadari bahwa ternyata Indonesia hanya dijadikan tempat sampah untuk membuang cost hancurnya ketahanan pangan di AS dan Eropa akibat meningkatnya industri biofuel disana. Bukan hanya itu, ketahanan pangan Indonesia juga ikut hancur. Mirip seperti yang terjadi di AS dan Eropa beberapa tahun lalu.
Kita harus waspada soal ini…