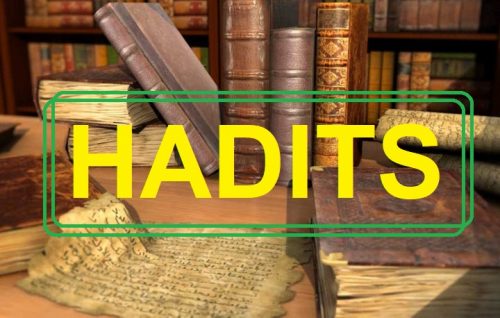Jakarta, Aktual.com – Sebagian besar ahli hadits menegaskan bahwa hadits dhaif boleh di terima dalam fadhail al-‘amal. Di antara ulama tersebut, ada Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Sayyid Al-Nas dalam kitab Uyun Al-Atsar, Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dalam Al-Ta’zhim al-Minnah, Imam Al-Iraqi dalam Alfiyyah Hadits, Imam Sakhawi dalam Al-Qaul Badi’, Imam Nawawi dalam Kitab Al-Adzkar, dan ulama lainnya.
Namun, dalam menggunakan hadits dhaif tersebut, ada tiga syarat yang disebutkan oleh Imam Sakhawi dalam Qaul Badi’: Pertama, hadits tersebut tidak sangat lemah; gambaran sangat lemah tersebut terjadi jika setiap jalur sanad pada hadits tersebut pasti ditemukan rawi yang dinilai berbohong, atau tertuduh berbohong. Kedua, isi dari hadits tersebut, masuk kepada dalil shahih yang lain yang bersifat umum. Ketiga, tidak meyakini kesunahan amalan tersebut sebab hadits dhaif, tapi keyakinan orang yang mengamalkan hanya sebatas hati-hati, agar tidak kelewatan untuk mendapatkan fadhilah yang dijanjikan oleh hadits tersebut.
Pengaplikasian syarat-syarat ini, diberikan contoh oleh Al-Muhaddits Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi (w. 1304 H) dalam Dzafar Al-Amani dengan penggunaan sebuah hadits riwayat Imam Tirmidzi sebagai dalil untuk mengumandangkan adzan secara perlahan, dan mengumandangkan iqamah dengan cepat.
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui jalur Abdul Mun’im bin Nuaim, dari Yahya bin Muslim, dari Al-Hasan dan ‘Atho, dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:
يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر.
“Wahai Bilal, jika kamu mengumandangkan adzan, maka kumandangkan adzan secara perlahan, dan jika kamu mengumandangkan iqamah maka percepatlah iqamahmu.”
Riwayat ini oleh Imam Tirmidzi dinilai lemah, sebab jalur sanadnya hanya diketahui melalui satu jalur, yakni jalur Abdul Mun’im, dan sanadnya dinilai majhul. Terlebih, Al-Daraquthni dan sekelompok ulama hadits yang lain, juga menilai Abdul Mun’im sebagai perawi yang lemah, dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Mun’im dalam sunan tirmidzi, hanya hadits ini saja, tidak ada yang lain.
Meski begitu, ulama fiqih tetap menilai bahwa mengumandangkan adzan secara perlahan dan membaca iqamah secara cepat sangat dianjurkan.
Anjuran ini bukan hanya sebatas karena hadits dhaif tersebut, tapi dikuatkan dengan adanya konsensus para sahabat yang mengamalkan kandungan dari hadits tersebut.
Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi dalam Muhadzab yang mengutip ucapan Sahabat Umar bin Khattab kepada muadzinnya, Abu Zubair: “Jika anda adzan, maka kumandangkan secara perlahan, dan jika anda iqamah bacalah secara cepat.” (3/108).
Jadi penggunaan hadits tersebut, sesuai dengan syarat yang disebutkan diawal: haditsnya tidak sangat lemah sebab Abdul Munim hanya dinilai lemah, bukan berdusta, dan ada dalil shahih yang dalam kasus ini adalah konsensus (ijma’) sahabat dalam mengamalkan amalan yang sesuai dengan kandungan hadits tersebut.
**
Memang banyak ulama yang secara gamblang mengatakan bahwa hadits dhaif boleh diterima untuk fadhail al-‘amal, tapi diantara mereka ada perbedaan pendapat dalam memahami makna dari bolehnya hal tersebut.
Beberapa di antara ulama tersebut mengartikannya dengan menerima hadits-hadits dhaif untuk fadhail al-‘amal yang amalannya sudah tetap melalui hadits shahih.
Dalam artian, amalan tersebut sudah memiliki hukum tetap sebagai amalan sunnah melalui hadits shahih. Kemudian, datang hadits dhaif sebagai penjelas kadar pahalanya jika amalan tersebut tentang motivasi beramal (targib), atau kadar hukumannya jika amalan tersebut tentang meninggalkan perkara yang buruk (tarhib).
Dari sini difahami, bahwa dengan menerima hadits dhaif, bukan berarti itu kita menetapkan hukum dengan hadits dhaif. Namun, hanya sebatas menjadi penjelas kadar pahala, atau hukuman.
Imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar dari golongan Syafi’iyyah dan Imam Ibnu Al-Humam dalam kitab Fath Al-Qadir dari golongan Hanafiyyah, memiliki pandangan yang berbeda dari pendapat yang sebelumnya.
Kedua ulama tersebut, berpendapat bahwa hadits dhaif bisa dijadikan dasar untuk menetapkan suatu amalan dihukumi sunnah, atau dianjurkan. Jadi menurut beliau berdua, fungsi hadits dhaif tidak hanya sebatas menjadi penjelas kadar pahala maupun kadar hukuman.
Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar mengatakan:
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل بالحديث الضعيف بالفضائل والترغيب ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، انتهى.
“Ulama dari ahli hadits dan ahli fiqih, dan selain dari mereka mengatakan: diperbolehkan dan dianjurkan untuk mengamalkan hadits dhaif dalam ranah fadhail dan motivasi beramal, selama hadits itu tidak palsu. Sedangkan untuk ranah hukum seperti halal, haram, jual beli, pernikahan, perceraian, dan selain dari itu, maka tidak boleh diamalkan kecuali dengan hadits shahih atau hasan, kecuali hadits dhaif yang digunakan hanya sebatas dalam rangka kehati-hatian.”
Di sinilah muncul sebuah masalah penting.
Beberapa ulama, menganggap ibarat Imam Nawawi ini bermasalah. Karena istihbab (anjuran) adalah hukum dari hukum syariat yang lima. Jika dia dianjurkan, maka ada nilai kebolehan melakukan. Kok bisa hal yang demikian menggunakan hadits dhaif? Bukankah kita sudah sepakat jika hadits dhaif hanya digunakan untuk fadhail, bukan boleh atau tidaknya melakukan sesuatu?.
Imam Al-Muhaqqiq Jalaluddin al-Dawani dalam kitab beliau Unmudzaj al-Ulum, kitab yang berisi berbagai masalah dari berbagai cabang ilmu, memberikan jawaban atas masalah ini yang diletakan pada masalah pertama. Ibarat Jalaluddin al-Dawani ini juga dikutip oleh Imam Ibnu ‘Alan Al-Shiddiqi dalam Futuhat Al-Rabbaniyyah.
Pada masalah pertama itu, beliau memberikan deskripsi masalahnya: bahwa ulama sepakat jika hadits dhaif tidak digunakan untuk menetapkan hukum syariat. Kemudian di antara mereka ada yang menyebut bahwa boleh bahkan dianjurkan untuk mengamalkan hadits dhaif pada fadhail al-amal, di antaranya ada Imam Nawawi dalam kitab al-Azkar (sebagaimana ibarat yang sudah tertera di atas).
Beliau menilai, ibarat Imam Nawawi ini terdapat keganjalan; karena memperbolehkan amal atau menganjurkannya merupakan bagian dari hukum syariat yang lima (wajib, sunnah/anjuran, mubah, makruh, haram), jika dianjurkan melakukan sesuatu atas dasar hadits dhaif, maka sama saja kita menetapkan anjuran dengan hadits dhaif, dan ini bertentangan dengan kesepakatan di awal, bahwa hadits dhaif tidak digunakan pada perkara hukum.
Beberapa ulama, ada yang berusaha mendudukkan ibarat Imam Nawawi agar mudah difahami. Ada yang memberikan penjelasan, bahwa maksud Imam Nawawi adalah: jika ada hadits shahih yang sudah ditetapkan pada suatu keutamaan beramal, maka boleh meriwayatkan hadits dhaif pada bab ini. Namun, ini terlihat jauh dari zahir ibarat Imam Nawawi.
Imam Al-Dawani menilai penjelasan itu sama sekali tidak memiliki kaitan dengan ibarat Imam Nawawi. Sebab jauh sekali perbedaan antara diperbolehkan amal atau dianjurkan, dengan sekedar mengutip hadits atau meriwayatkannya.
Karena realita pada kitab-kitab hadits, meskipun ada amalan yang belum ditetapkan dengan hadits shahih, tentu boleh-boleh saja mendatangkan hadits dhaif dengan tujuan sekedar mengutip dan memberikan keterangan jika hadits tersebut lemah. Hal yang seperti ini sangat banyak ditemukan pada buku-buku hadits.
Menurut Al-Dawani, jawaban yang pas adalah, jika kita menemukan hadits dhaif tentang suatu amalan dan amalan tersebut tidak memiliki sisi yang dapat membuat amalan tersebut dimakruhkan atau diharamkan, maka diperbolehkan untuk mengamalkannya; sebab tidak ada kemungkinan dosa di sana, hanya ada kemungkinan boleh atau dianjurkan untuk dilakukan. Maka yang lebih hati-hati, supaya tidak terlewat untuk mendapatkan pahalanya, agar lebih baik diamalkan saja.
Selanjutnya al-Dawani memperinci setiap kemungkinan. Jika hadits dhaif itu mengandung dua kemungkinan hukum; haram dan sunnah, maka tidak ada anjuran di sana, hukumnya tetap haram. Saya tidak mengetahui, bagaimana gambaran ini terjadi. Selanjutnya beliau memperinci, antara makruh dan sunnah, dst. Yang intinya, selama masih pada batas anjuran tersebut hanya memiliki kemungkinan makruh yang ringan, maka masih boleh di amalkan. Adapun makruh yang sangat, dan keatasnya, kemungkinan diperbolehkan untuk diamalkan sudah tidak ada.
Di akhir, Al-Dawani memberi kesimpulan, bahwa kebolehan mengamalkan amalan diperbolehkan dari dalil lain selain dari hadits dhaif, dan ishtihbab (menganjurkan amalan) juga diketahui melalui kaidah syariat (bukan dari hadits dhaif) yang menganjurkan untuk hati-hati dalam beragama, yang dalam kasus ini, kita berhati-hati agar tidak kelewatan mendapatkan pahala yang terkandung dalam hadits dhaif.
Maka hasilnya, sebetulnya hadits dhaif tidak menetapkan hukum apapun. Hanya saja pada hadits tersebut terjadi kesamaran, apakah dianjurkan untuk diamalkan atau tidak? Karena agama mengajarkan hati-hati, maka dianjurkan mengamalkan hadits dhaif, agar setidaknya kita mendapatkan pahalanya, toh seandainya itu pahalanya tidak ada, kita juga tidak berdosa.
**
Menurut Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi, Pendapat Al-dawani bahwa hadits dhaif tidak dapat digunakan untuk menentukan hukum secara mutlaq, tidaklah tepat. Karena ulama-ulama hadits seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan muridnya; Imam Sakhawi, berpendapat boleh menggunakan hadits dhaif dengan syarat yang sudah disebutkan.
Mazhab Abi Hanifah juga lebih mengedepankan hadits dhaif dari pada harus menggunakan pendapat atau qiyas.
Imam Ahmad bin Hambal juga lebih senang menggunakan hadits dhaif dalam menentukan hukum, jika tidak ada hadits lain selain hadits tersebut.
Maka penggunaan hadits dhaif ini sebetulnya diperselisihkan atas 3 pendapat: ada ulama yang tidak memperbolehkan penggunaannya pada hukum, seperti al-Dawani. Ada ulama yang memperbolehkannya dengan syarat seperti Imam Al-Sakhawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan terakhir, boleh secara mutlaq.
**
Fahrizal Fadil
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin