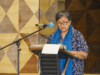Beberapa pihak pun menganggap bahwa kondisi demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran, kalau tidak dikatakan sebagai kondisi darurat demokrasi.
Dalam pasal penghinaan Presiden misalnya, kekhawatiran pembungkaman masyarakat pun sudah dimulai sejak KUHP belum disahkan. Dalam beberapa tahun belakangan, para pengkritik pemerintah pun dihantam dengan berbagai dalih hukum, mulai dari makar hingga UU ITE.
Tak pelak, dengan sedang digodoknya RKUHP yang memuat masalah penghinaan presiden pun membuat sejumlah pihak khawatir jika pada praktiknya hal ini justru malah kebablasan atau disalahgunakan.
Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengatakan, aparat penegak hukum dapat secara leluasa menjerat hukum orang yang sebenarnya hanya bermaksud menyampaikan kritik.
Meskipun bermotif penyampaian kritik, tidak tertutup kemungkinan jika nantinya terdapat pengkritik yang tetap diproses hukum atas dasar telah melakukan penghinaan.
“Memang banyak sekali kasus yang murni kritik, tetapi ditarik ke ranah penghinaan. Jadi sudah jangan mendongeng kepada kami soal kasus penghinaan. Kalau mau kasih unjuk mana penghinaan mana kritik, itu bohong,” jelasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun misalnya, menyebut hal ini sebagai proyek jangka pendek yang justru mengorbankan demokrasi itu sendiri. Menurut Refly, sangat wajar jika seorang Presiden akan terus diikuti oleh kritik sepanjang ia bekerja, mengingat tingginya jabatan tersebut.
“Yang harus kita jaga ini, demokratisasi kita. Praktisnya kan kita ganti, bisa berganti sesuai dengan periodenya. Tapi demokrasinya harus systemable, harus sesuai sistem terus,” jelasnya.
Pun demikian dalam masalah hak imunitas dan pemanggilan paksa oleh DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Perpaduan antara pasal penghinaan Presiden dengan hak imunitas dan panggilan paksa DPR pun disebut Ray Rangkuti sebagai alat tukar guling saja bagi parpol. Menurutnya, sangat aneh jika sebuah parpol menolak pasal penghinaan presiden, tapi di sisi lain justru menerima hak imunitas bagi anggota DPR.
Beberapa parpol seperti Gerindra, PKS dan PAN memang secara tegas menolak keberadaan pasal penghinaan Presiden. Sayangnya sikap mereka justru berbalik 180 derajat saat berbicara tentang hak imunitas DPR.
Ray pun menyoroti PDIP yang berada dalam posisi pendukung RKUHP dan UU MD3. Baginya, partai banteng merupakan sentral bagi keberadaan kedua hal tersebut.
Menurut Ray, sikap ketiga partai penolak pasal penghinaan Presiden akan melunak lantaran PDIP telah menyepakati UU MD3.
“Semua jadi setuju, mau enggak mau sekarang setuju karena mereka enggak punya dasar moral lagi untuk menolaknya (pasal penghinaan presiden),” jelasnya.
Dengan demikian, RUU KUHP dan UU MD3 pun hanya menjadi alat tukar menukar saja bagi partai politik, baik parpol penguasa maupun oposisi.
“Ini soal tukar menukar aja,” ujar Ray.
Hal ini pun diyakini oleh peneliti hukum dan Deputi Direktur PARA Syndicate, Agung Sulistyo, akan membuat kualitas demokrasi Indonesia semakin terdegradasi. Menurutnya, kondisi ini sangat kontras dengan 20 tahun silam yang menjadi kelahiran era reformasi. Pada masa itu keran demokrasi sangat dibuka lebar dengan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 7/1998 sebagai dasarnya.
Melalui TAP MPR 7/1998 ini, Agung mengatakan, kebebasan berpendapat, berekspresi dan menyalurkan aspirasi ditanamkan dengan sungguh-sungguh.
“Sayangnya perjalanan ini tidak hanya tersendat tapi mungkin berputar arah mundur. Padahal banyak anggota saat ini merupakan aktivis saat reformasi,” kata Agung menyesali.
Nebby/Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby