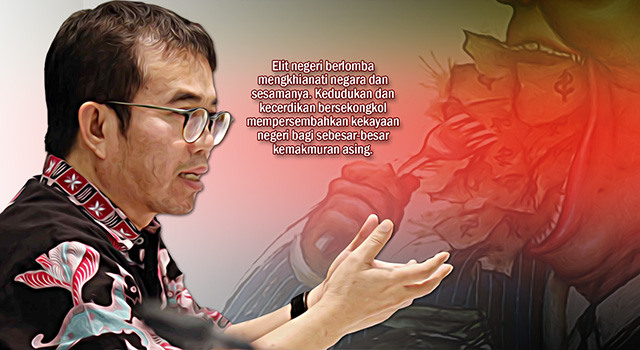Jakarta, Aktual.com – Saudaraku, apa yang sengit kita pertentangkan ini hanyalah pepesan kosong. Kemana saja kita menghadap, yang berjaya di banyak tempat adalah kedangkalan.
Ketika kebenaran ditentukan oleh jumlah; dan ketika jumlah terbesar adalah ketidakhirauan dan ketidakberdayaan, kebenaran itu mudah dimenangkan oleh raksasa manipulasi impresi.
Kebebalan keburukan menguasai sendi-sendi kehidupan. Ruang publik disesaki sampah komedi omong, kerapatan parlemen dirayakan kesenyapan gagasan, program-program pemerintah disibukkan oleh involusi kelambanan dan kemubaziran.
Elit negeri berlomba mengkhianati negara dan sesamanya. Kedudukan dan kecerdikan bersekongkol mempersembahkan kekayaan negeri bagi sebesar-besar kemakmuran asing. Rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam perluasan korupsi. Ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela; kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.
Di zaman kalabendu, yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, kehancuran tata nilai dan keteladanan, situasi “anomali” (a-nomos, ketidakteraturan) dianggap sebagai “normal” (norm, keteraturan). Aparatur negara saling serang memperebutkan “lahan jarahan”. Penegak hukum berjamaah melanggar hukum. Agama dimanipulasi untuk tujuan korupsi politik. Kesantunan gerak tutur menjadi topeng kebusukan susila.
Republik berjalan tanpa tuntunan kepanditaan, pancaran kesadaran agung para nahkoda republik untuk membawa bangsa keluar dari kegelapan. Sutasoma berkata, pemimpin tercerahkan tidak bisa dinilai dari penampilan citra lahiriyahnya. “Pancaran pengetahuan suci dan kebijaksanaan itu sendirilah yang menjadi tanda apakah seseorang itu tercerahkan atau tidak (tanpa memandang dia raja atau pandita dalam wujud lahirnya).”
Banyak orang berpenampilan pandita untuk menjual ayat dengan harga yang murah; membenarkan kejahatan politik dengan rekayasa statistika; mendidik orang untuk tujuan kesesatan dan kebencian.
Merajalelanya pandita palsu membawa bencana dan kemarau keteladanan. Sutasoma berkata, “Meskipun benar dikatakan bahwa murid haruslah mematuhi gurunya seperti mematuhi orang tuanya sendiri. Namun, jika guru bertindak jahat, maka akan ada kekeringan, hujan turun salah musim, panen-panen gagal, kesepuluh penjuru mata angin diliputi ketakutan, kejahatan terjadi di mana-mana, dan wabah penyakit berlangsung tanpa akhir.”
Banyak orang berambisi memimpin negeri tanpa memahami dan mencintai negerinya. Bagaimana bisa berempati terhadap penderitaan rakyat di keragaman pelosok tanah air, jika calon pemimpin nasional tidak pernah mengenali dan menjelajahi negerinya. Bagaimana bisa menghayati ideologi nasional, jika calon pemimpin bangsa tidak merasakan pahit getir sejarah perjuangan bangsa.
Banyak pemimpin salah asuhan: makan, minum dan bernafas dari kesugihan negeri ini, namun dengan mentalitas asing yang tega mengkhinati dan menjarah ibu pertiwinya sendiri. Benar juga kata John Lie, pahlawan nasional keturunan Tionghoa, Orang pribumi adalah orang-orang yang Pancasilais, saptamargais, yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan non-pribumi adalah mereka yang suka korupsi dan merugikan kepentingan nasional. “Mereka itu sama juga menusuk bangsa kita dari belakang. Maka patutlah mereka digolongkan orang non-pribumi.”
Banyak orang merasa pantas jadi pemimpin tanpa keterujian rekam jejak dan kejernihan visi. Semua nilai dan kepantasan disusutkan pada nilai uang dan popularitas. Tawaran visi diremehkan ketika tawaran “gizi” diutamakan.
Partai-partai politik membentangkan karpet merah kepada orang berduit. Ketika orang berduit bisa mendiktekan kemauannya kepada partai politik, atau bisa langsung ditempatkan di pucuk pimpinan organisasi, pada saat itu pula partai politik sebagai institusi kolektif yang memperjuangkan aspirasi kolektif roboh.
Banyak orang yang menjanjikan perbaikan bagi negeri, tetapi justru dengan menempuh cara-cara yang merusak negeri. Padahal, untuk tiba pada kebenaran, orang harus sudah berada di jalan yang benar. Bagaimana bisa berhasil menjalankan operasi demokrasi, jika kepemimpinan dalam partainya sendiri dijalankan dengan cara-cara tirani. Bagaimana bisa bertanggung jawab memimpin Republik, sedang tanggung jawab dalam kedudukan sebelumnya tak mampu ia tunaikan. Bagaimana bisa memerangi politik uang, jika jalan partai untuk memenangkan kontestasi pemilihan pun ditempuh dengan menerima uang sogokan.
Bagaimana kita bisa percaya, demokrasi kita berada di jalan yang benar? Setelah belasan tahun reformasi digulirkan, jalan sejarah kita justru menjelang kebuntuan state manque dalam nubuat Clifford Geertz: “sebuah negara yang tak kunjung menemukan bentuk politik yang cocok bagi watak rakyatnya, tersandung dari percobaan institusional yang satu ke yang lain.
Jalan buntu ini terjadi karena kemiskinan imajinasi kita. Reformasi sosial acapkali direduksi sekadar reformasi prosedural; dan pilihan-pilihan prosedur itu pun seringkali diambil secara serampangan dari model luar, tanpa usaha kontekstualisasi ke dalam sistem sosial-budaya kita.
Padahal, jantung masalah kita ada pada sistem pemaknaan—sebagai inti budaya. Apapun prosedur yang kita ambil, jika sistem pemaknaan mengalami kerusakan tidak akan menghasilkan perubahan substantif.
Kerusakan sistem makna sebagai sistem budaya kita terlihat dari bahasa yang dominan di ruang publik: bahasa politik dan bahasa ekonomi. Bahasa politik dan ekonomi kita hanya mengenal satu pertanyaan: “siapa yang menang?” dan “apa untungnya?” Ruang publik kita jarang mengenal pertanyaaan budaya yang mempertanyakan “apa yang benar?”
Singkat kata, kita perlu meruwat Republik dengan revolusi budaya, revolusi mental dalam cara kita memaknai kehidupan publik. Soekarno berkata, “Suatu negara dapat berdiri tanpa tank dan meriam. Tetapi suatu bangsa tidak mungkin eksis tanpa keyakinan.” Keyakinan yang tumbuh melalui sistem makna yang tunduk pada imperatif moral bahwa rasionalitas kepentingan pribadi tidak boleh dibayar oleh irasionalitas kehidupan publik.
Seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”
(Yudi Latif, Makrifat Pagi)