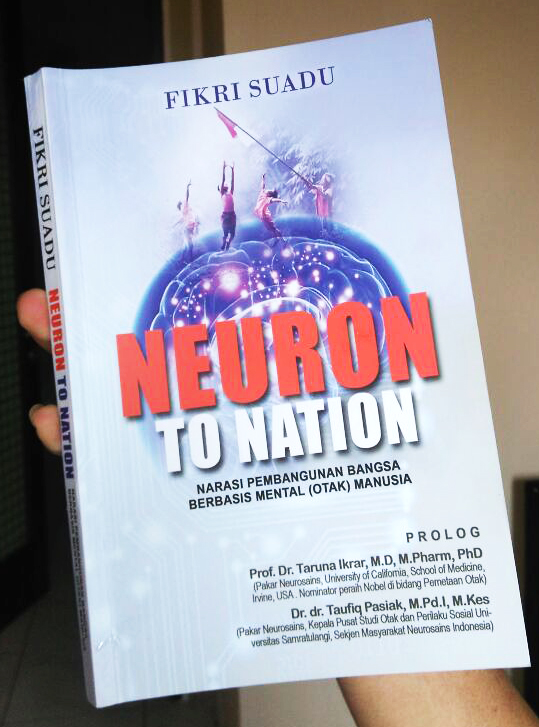Begitu kuatnya otak emosional dan lemahnya akal sehat, termasuk di ranah politik nasional saat ini, pertanda bahwa otak normal belum tentu disertai kuatnya karakter dan integritas sebuah bangsa. Otak sehat lah yang akan menempatkan fungsi karakter dan integritas sebagai bagian yang cukup penting.
Sejak Pilpres 2014 hingga Pilgub DKI Jakarta 2017, ada sebuah gejala menarik. Ada banyak anggota warga masyarakat yang sejatinya tidak berpartai atau bergabung dengan suatu partai politik tertentu, namun sikap partisan politik atau pemihakannya pada sosok yang dijagokannya sebagai calon presiden atau calon gubernur, bukan main fanatiknya, bahkan cenderung membabi-buta. Menjadi lover atau pemuja seorang calon yang dia dukung seraya jadi hater atau pembenci calon pesaing dari sosok yang dia jagokan. Gejala apa ini?
Dokter Taufiq Pasiak, pakar Neurosains, punya penjelasan yang cukup menarik. Menurut dokter Taufiq sepertinya ada suatu wabah dalam cara berpikir yang sedang melanda rakyat Indonesia. Suatu wabah pikiran yang membagi manusia Indonesia menjadi dua kelompok. Para pecinta alias hater, dan para pembenci atau hater. Namun, keduanya sejatinya mengidap penyakit yang sama, penyakit otak emosional.
Dalam kata pengantar untuk buku karya dokter Fikri Suadu, Neuron to Nation, Narasi Pembangunan Bangsa Berbasis Mental (Otak) Manusia, dokter Taufiq meminjam istilah dari pakar Neurosains Daniel Golleman,, yaitu Amiygdala hijacking, alias pembajakan akal sehat.
Begitulah. Baik pecinta maupun pembenci sama-sama kehilangan akal sehat (rasio) mereka. Celakanya, menurut dokter Taufiq, sifat ini melanda hingga ke lapisan masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi. Bahkan juga melanda beberapa guru besar.
Baik pemuja maupun pembenci calon-calon presiden, gubernur, bupati dan walikota, sama-sama dikendalikan emosi atas pikirannya. Dalam istilah di kalangan pakar neurosains, kedua kelompok ini menjadi sasaran penguasaan amigdala atas korteks prefrontalis. Jadi, apa sesungguhnya yang ada di otak para partisan politik itu? Sebuah penelitian di Amerika Serikat seperti yang dilakukan oleh Drew Wasten, Stephan Hamann, dan Clin Kilts, dalam bukunya Political Brains, ternyata di negeri maju dan demokratis macam Amerika pun, sebagian besar masyarakat Amerika masih dipengaruhi oleh Otak Emosional.
Misal, meskipun seorang calon presiden seperti John Kerry terbukti melalui sebuah penelitian telah membuat dua pernyataan yang tidak konsisten terkait soal kebijakan Amerika di Irak terkait sanksi ekonomi terhadap Irak, sementara pada kesempatan yang berbeda, Kerry membuat pernyataan kebalikannya, ternyata inkonsistensi Kerry tidak berarti apa-apa di mata para pendukungnya.
Dengan makna lain, jika sudah mendukung seorang calon, maka dusta, tidak konsisten dan bahkan manipulatif yang dipertunjukkan si calon, tidak berarti apa-apa bagi para pendukungnya yang masuk kategori the lovers tersebut.
Alhasil, otak politik persis seperti otak orang yang sedang jatuh cinta. Semua terasa indah, bagus dan tanpa cela. Lantas, apa sih ciri-ciri otak emosional (otak yang bekerja atas arahan dari emosi) itu? Pertama, cepat dan dan mudah membuat kesimpulan atas dasar fakta dan data yang tidak valid. Kedua, cenderung merasa terancam, dalam arti merasa selalu seperti diancam, tidak nyaman, dimata-matai dan melihat lingkungan sekitar sebagai gangguan. Ketiga, cenderung suka pada rasa aman, dan maunya yang aman aman saja lias safety players.
Keempat, tidam mau rugi. Atau cenderung lebih baik tidak mendapatkaan sesuatu daripada kehilangan sesuatu. Kelima, cenderung menyukai yang sudah akrab, dan sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari, kaku, tertutup dan tidak ingin mendengar pendapat baru. Keenam, ingin yang serba gampang, tidak mau usaha, dan ingin enaknya saja. Ketujuh, mudah terbuai dengan hal-hal yang indah, meskipun tahu itu hanya pencitraan , manipulasi atau kebohongan.
Pada akhirnya ini bisa berkembang jadi kepribadian dan cara berpikir atau mindset. Menurut dokter Taufik, otak emosional para partisan politik itu memang dirangsang oleh kampanye, propaganda dan indoktrinasi yang dilancarkan tim pemenangan calon yang diusungnya. Namun sifat dasar otak emosional dengan tujuh ciri tadi tetap melekat. Sehingga diperlukan kerja keras untuk mengubah cara berpikir para partisan politik tersebut.
Pandangan dokter Taufiq maupun dokter Fikri sang penulis buku Neuron to Nation, nampaknya bukan bermaksud berkutat menelaah soal otak manusia. Ada sesuatu yang lebih menggelisahkan daripad soal itu. Yaitu bagaimana sebuah bangsa, seperti masyarakat Indonesia berotak sehat sekaligus berkarakter.
Neuron to Nation mengandaikan bagaimana perubahan pada bangsa bermula dari rekayasa otak manusia, dalam arti usaha mengoptimalkan fungsi otak yang tidak sekadar normal, melainkan juga sehat. Sebab manusia yang punya otak sehat, berarti menempatkan fungsi karakter dan integritas sebagai bagian penting. Sehingga otak sehat, berarti otak normal plus karakter atau integritas.
Rupanya yang jadi kegelisahan pokok dokter Taufiq dan dokter Fikri, Karena selama ini kecerdasan yang lahir dari otak yang normal tidak serta merta melahirkan manusia yang punya integritas. Banyak orang yang normal otaknya tapi tidak memiliki integritas dan karakter.
Solusinya tiada lain kecuali terus-menerus memupuk kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua dokter lulusan Universitas Samratulangi Manado itu meyakini pandangan bahwa ada hubungan yang lurus antara ketrampilan berpikir kritis dan kreatif dan kemajuan bangsa.
Maka, spiritualitas merupakan komponen dalam membangun otak sehat. Integritas dan karakter bangsa Indonesia erat kaitannya dengan Sila-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Itulah unsur penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia.
Menyimak jalan berpikir buku Neuron to Nation, gejala kuatnya dominasi dan kendali emosi dalam pikiran para partisan politik seperti terlihat baik dalam pilpres maupun pilgub, jangan-jangan mengisyaratkan sinyalemen kedua dokter muda tadi. Betapa di negeri kita saat ini, begitu banyak orang yang berotak normal, namun tidak berotak sehat.
Menguatnya gejala pemuja dan pembenci dalam pemilu dan pemilakada, menandakan lemahnya karakter dan integritas kita sebagai bangsa. Kalau begitu, seruan Bung Karno, Presiden RI pertama, perlunya the National and Character Building, kiranya masih tetap relevan hingga sekarang.
Agaknya, tidak cukup hanya dengan beretorika tentang perlunya Revolusi Mental.
Hendrajit.