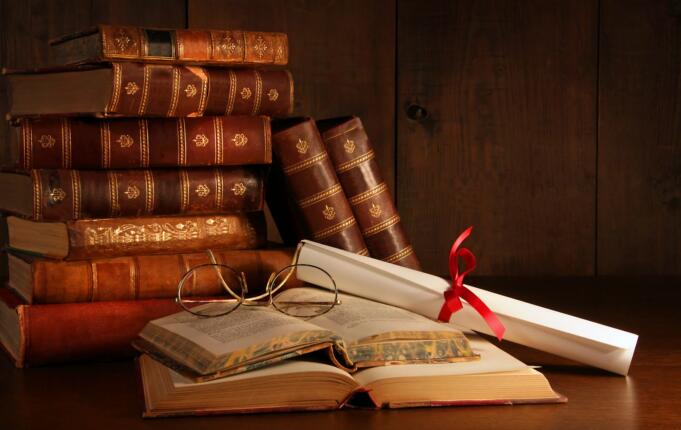Jakarta, Aktual.com – Syekh Muhammad Awwamah, dalam karyanya yang berjudul: Atsar Al-Hadits Al-Syarif fi Ikhtilaf Al-Aimmah Al-Fuqaha (Pengaruh Hadits Terhadap Perbedaan Pendapat Ulama Fiqih) menyebutkan secara garis besar setidaknya satu dari dua alasan ini menjadi sebab para ahli fiqih berbeda pendapat dalam memahami suatu teks hadits: perbedaan kekuatan akal pada setiap orang, dan lafadz Hadits yg mungkin untuk difahami lebih dari satu makna.
Sebab pertama bisa difahami secara jelas, bahwa setiap orang memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selain kasus memahami teks misalnya dilihat dalam olahraga, kita akan melihat dengan jelas bahwa tidak setiap pemain bola sehebat Lionel Messi, atau tidak semua pemain basket sekeren Michael Jordan.
Kekuatan akal yang berbeda-beda bisa terjadi sebab beberapa sebab, bisa karena bawaan dari lahir, atau pergaulan dan keadaan budaya sekitar dengan tingkat literasi yang berbeda, atau karena sering dilatih layaknya seorang hakim yang semakin lama praktek, semakin mengerti dan tajam analisisnya dalam menjatuhkan sebuah hukum.
Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dalam kitab Syarah Alfiyah Al-Atsar memberikan gambaran terhadap ilmu yang ada pada susunan hadits seperti laut yang tiada tepinya. Setiap masa ke masa, selalu ada saja alim ulama yang membuka sebuah makna baru yang ia fahami dengan metode yang benar pada matan hadits yang bahkan ulama terdahulu belum ada yang memahami makna tersebut. Ini menunjukkan dengan jelas, bahwa perbedaan kekuatan akal setiap ulama menjadi sebab bedanya pendapat antara mereka, juga menunjukkan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja yang ia kehendaki, tanpa terikat tempat dan waktu.
Sebab kedua dari perbedaan pendapat para ulama terhadap suatu hadits, muncul karena lafadz hadits yang mungkin difahami dengan beberapa makna.
Kejadian ini banyak dijumpai. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam soal ini, Syekh Muhammad Awwamah menetapkan dua syarat hingga hadits tersebut sah difahami dengan beberapa makna: pertama, perbedaan pandangan itu diterima dari segi bahasa Arab, dalam artian, lafadz yang ada pada hadits, terdapat beberapa makna yang sah-sah saja diartikan dengan salah satu diantaranya. Kedua, makna cabang yang difahami tidak bertentangan dengan hukum yang sudah paten dengan teks dalil yang lainnya.
Jika terjadi kasus hadits yang dapat difahami dengan beberapa makna, maka tugas seorang ulama untuk mengumpulkan makna yang difahami, kemudian berusaha untuk membahas dalil pendukung lainnya untuk menguatkan salah satu makna yang menjadi pilihannya.
Dalam soal ini, Syekh Muhammad Awwamah memberikan contoh pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
“Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah.”
Pada hadits ini, para ahli fiqih berbeda pendapat dalam memaknai “selama belum berpisah”, apakah maknanya yang diinginkan adalah berpisahnya badan antara dua orang yang bertransaksi dari tempat akad, sehingga jika sudah saling sepakat kemudian berpisah, akad tersebut sudah terjadi, dan tidak berhak bagi salah satu pihak memutuskan akad kecuali dengan persetujuan pihak yang lain. Makna ini dipilih oleh Imam Syafi’i.
Atau makna “selama belum berpisah” diartikan dengan selesainya ucapan akad yang digunakan. Dalam artian, selama mereka masih dalam proses akad, maka boleh salah satu diantara keduanya untuk membatalkan akad, dan jika sudah sepakat, maka tidak boleh salah satu diantara mereka untuk membatalkan akad kecuali dengan izin dari pihak lain. Khiyarnya sudah hilang meskipun mereka masih dalam tempat akad. Pendapat ini dipilih oleh Imam Hanafi.
Masing-masing dari golongan memiliki dalil dan argumentasi yang sama kuatnya. Imam Syafi’i menggunakan dalil nash dan analisa yang tajam, begitu juga Imam Hanifah yang melakukan hal yang sama.
Dalil pendukung yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam memilih makna tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Umar, bahwa beliau jika membeli sesuatu, dan sudah terjadi akad, beliau menjauh beberapa langkah, agar khiyar tersebut hilang, dan jika masih ada kebutuhan yang lain untuk dibeli, beliau kemudian mendekat kembali. Dengan ini dan beberapa dalil pendukung lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu’, Imam Syafi’i mengambil makna tersebut, karena apa yang difahami oleh Sahabat terhadap teks hadits lebih unggul dari pemahaman lainnya.
Adapun Imam Abu Hanifah menggunakan dalil surat Al-Nisa ayat 29:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”
Menurut Imam Abu Hanifah, dengan ayat itu difahami bahwa tetapnya akad asalnya adalah saling suka. Dan tanda saling suka itu dilihat dari ijab qabul. Maka jika sudah ijab qabul, sudah selesai khiyar diantara keduanya.
Makna yang diberikan Abu Hanifah bahwa kalimat “ma lam yatafarraqa” pada hadits tidak diartikan dengan berpisahnya badan tidaklah bertentangan dengan penggunaan bahasa, karena nyatanya ada beberapa ayat yang menggunakan kalimat “tafarruq” namun tidak diartikan dengan berpisahnya badan, seperti Surat Ali Imran ayat 103:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا
Artinya, “Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai berai!”
Dalam Tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengutip tafsiran Abdullah bin Mas’ud terhadap ayat ini: “Maknanya adalah menjaga kekompakan, dan tidak bercerai berai.”
Contoh kecil ini sudah cukup memberikan bukti bahwa ada hadits yang lafadznya mungkin memiliki beberapa makna, dan menjadi sebab perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih.
Syekh Muhammad Awwamah mencukupkan dengan contoh tersebut, dan memberikan closing statementnya dengan sebuah peringatan, bahwa semua hukum syariat yang digali hasilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka ia adalah bagian dari agama ini. Sebagaimana kedua sumber itu adalah bagian dari agama, maka hukum yang difahami dari keduanya dengan metode yang benar juga bagian dari agama.
Oleh karenanya, fiqihnya para imam Mazhab yang terdiri dari puluhan ribu hukum dengan berbagai masalah, itu semua merupakan hasil dari jerih payah mereka dalam memahami Al-Quran dan Hadits. Pendapat itu bukan berasal dari egoisme akal mereka. Maka jika kita katakan, ini fiqih Imam Syafi’i, ini Fiqih Maliki, maka yang dimaksud adalah hukum yang difahami oleh mereka atau dengan metode pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena fiqih menurut bahasa berarti pemahaman, sebagaimana yang telah masyhur.
Dengan kaidah sederhana ini, kita akan faham kekeliruan beberapa orang yang menyebut atau menamai buku mereka dengan fiqih Sunnah, atau fiqih kitab dan Sunnah. Mereka ingin menipu masyarakat, seolah “dagangan” mereka berasal dari distributor terdekat. Padahal isinya adalah pemahaman fulan dan fulan yang bahkan kita tidak mengenal siapa mereka dan siapa guru mereka. Hingga nanti akhirnya, masyarakat luas menjauh dari fiqihnya Imam Syafi’i dan Imam mazhab lainnya.
Sebagai penutup, ada sebuah kisah tentang orang yang meminta fatwa kepada seorang Syekh. Saat ingin memberikan jawaban, Syekh tersebut bertanya: “Anda ingin aku beri jawaban dari Al-Quran atau dari pendapat Imam Syafi’i?”
Sang penanya tersebut cerdas, ia menjawab dengan jawaban yang begitu menohok: “Aku ingin jawaban dari Imam Syafi’i. Karena pemahaman Imam Syafi’i terhadap Al-Quran dan Sunnah lebih aku percayai dari pada pemahaman anda terhadap kedua sumber dalil tersebut.!” Syekh tersebut diam mendengar jawaban penanya.
**
Disarikan oleh Fahrizal Fadil dengan beberapa tambahan dari kitab Atsar Al-Hadits Al-Syarif fi Ikhtilaf Al-Aimmah Al-Fuqaha hal 136-154. Madinah Buuts Al-Islamiyyah.
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin