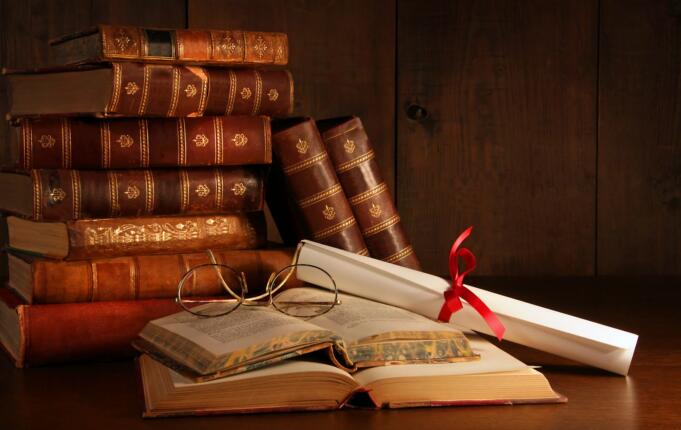Al-Ramahurmuzi, orang yang pertama kali menulis kitab mustalah hadits yang berjudul al-Muhaddits al-Fashil, dalam bukunya tersebut menuliskan sebuah kisah, yang kemudian kisah itu juga ditulis oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam Adab al-Faqih wa al-Mutafaqqih.
Ada seorang perempuan ikut menyimak sebuah majlis yang dihadiri para pembesar ilmu hadits pada zamannya. Di majlis itu, ada Yahya bin Ma’in, guru Imam al-Bukhari yang bergelar Maha Guru ilmu hadits (Syekh Al-Muhadditsin) pada masanya, ada juga Abu Khusaimah (w. 234) seorang perawi yang dinilai oleh Al-Khatib sebagai orang yang sangat terpercaya (tsiqah dan tsabat), ada juga Khalaf bin Salim (w. 231 H) yang dinilai oleh Ahmad bin Hambal sebagai orang yang tidak diragukan lagi kejujurannya, dan beberapa ulama lain yang sedang muzakarah tentang hadits.
Perempuan itu dengan asik menyimak mereka saling bertukaran riwayat dengan menyebutkan banyak jalur. Ada hadits yang diriwayatkan fulan, juga oleh fulan, hadits ini tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur fulan, dst.
Di tengah muzakarah itu, perempuan tersebut menanyakan sebuah masalah fikih. Ternyata ia datang dengan tujuan tersebut. Sebab masalah tersebut baru saja ia alami sendiri, yakni ia baru saja memandikan mayyit.
“Apakah orang yang sedang haidh boleh memandikan mayyit?” tanyanya kepada ulama hadits yang hadir.
Tidak ada satupun ulama hadits yang memberikan jawaban. Semuanya terdiam dan saling melihat satu sama lain. Di tengah majlis tersebut, ada seorang ulama fiqih, Abu Tsaur (w. 240 H), yang juga murid dari Imam Syafi’i. Ia menghadap kepada perempuan tersebut, dan memberi jawaban:
“iya, orang yang haidh boleh memandikan mayyit, karena ada hadits Utsman bin Ahnaf, dari Al-Qasim, dari Sayyidatina ‘Aisyah, Rasulullah bersabda: Sesungguhnya haidhmu tidak terletak di tanganmu. Juga ada hadits dari Sayyidatina Aisyah, bahwa beliau mengusap kepada Rasulullah dengan air dan beliau waktu itu sedang haidh.”
Abu Tsaur kemudian memberikan komentar pada hadits tersebut: “jika beliau boleh mengusap kepala dengan air terhadap orang yang masih hidup, maka mengusap mayyit lebih utama untuk dibolehkan.”
Setelah mendapatkan jawaban dari Abu Tsaur, ulama yang hadir menyetujui jawaban yang diberikan, dan kemudian mereka menambahkan: “ada juga riwayat dari fulan mengatakan begini, dari jalur ini begini, dari fulan haditsnya begini, dst.” dan ulama hadits tersebut terus menyebutkan secara mendalam tentang riwayat dan para perawi hadits. Perempuan yang bertanya tersebut nyeletuk: “anda semua dari tadi kemana saja?”
**
Salah satu cerita yang juga terkenal adalah ajakan Imam Ahmad bin Hambal kepada teman-teman sepantarannya yang merupakan ahli hadits yang begitu mendalami riwayat dan sangat senang untuk rihlah mencari hadits, tapi tidak memberikan perhatian lebih kepada ilmu fiqih, agar duduk bersama Imam Syafi’i dan mengambil faidah dari kelihaian beliau dalam memberikan hukum (istinbath) melalui Al-Quran dan Hadits.
Di antara ulama Hadits yang diajak oleh Imam Ahmad bin Hambal, ada Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Ma’in, Al-Humaidi, dan ulama lainnya. Setiap dari mereka merupakan pusat rujukan ilmu hadits di masanya, baik dari sisi hafalan, luasnya rujukan, dan kritik hadits.
Seandainya hanya dengan mengetahui hadits beserta jalurnya sudah cukup untuk mengetahui hukum –sebagaimana sangkaan beberapa orang yang baru saja belajar agama islam– maka tentu Imam Ahmad tidak akan mengajak mereka untuk duduk bersama Imam Syafi’i dan belajar dengan beliau.
Mereka yang diajak oleh Imam Ahmad, bukanlah sembarang orang. Tapi ahli hadits yang betul-betul ahli dalam bidangnya.
Lalu bagaimana adanya, jika ada orang yang hanya mengetahui satu dua hadits, lalu memaksakan diri untuk menyimpulkan hukum dari hadits tersebut, padahal dia sama sekali tidak punya pemahaman tentang cara menyimpulkan hukum dengan belajar ushul fiqih, atau bahkan pengetahuan haditsnya pun sangat terbatas dengan hafalan yang bisa dihitung dengan jari?
Berkali-kali guru-guru saya, memberikan peringatan keras, bahwa salah satu musibah di masa sekarang adalah sangkaan beberapa orang yang mengira pada setiap hadits atau ayat, ada satu hukum yang dihasilkan.
Padahal satu hukum, tidak lahir dari satu dalil. Ia merupakan proses panjang, dan penggabungan banyak dalil yang sudah dipelajari dan diteliti. Dengan mendatangkan dalil pendukung jika ada dalil yang terlihat zhahirnya kontradiksi, atau melihat mana hukum yang sudah dihapus (naskh mansukh), dan proses lainnya yang sangat panjang.
Setelah jerih payah semua ulama tersebut dengan melahirkan sebuah hukum, kemudian datang orang yang tidak sadar dengan kemampuan dirinya, lalu mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dan menyimpulkan hukum dengan sebuah dalil yang bahkan ia pun belum pernah meneliti dalil tersebut dengan serius. Allah Al-Musta’an.
**
Fahrizal Fadhil
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin