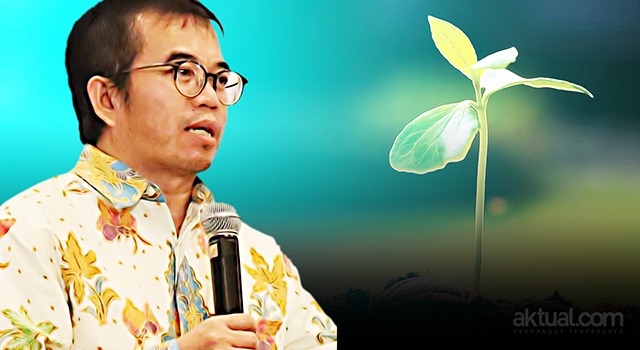Jakarta, Aktual.com – Saudaraku, rasa memiliki dan mencintai Tanah Air sebagai pancaran rasa syukur atas karunia Tuhan dapat menggelorakan semangat patriotisme, baik yang bersifat “negatif-defensif” (melawan musuh dan keburukan) maupun yang bersifat “positif-progresif” (mengolah potensi dan sumberdaya demi kemakmuran dan kejayaan bangsa).
Dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa, semangat patriotisme tersebut tidak hanya terpancar dari golongan mayoritas, malainkan juga dari berbagai asal-usul primordial. Kecintaan terhadap Nusa-Bangsa, tanpa mengenal asal-usul dan keturunan itu antara lain diperlihatkan oleh seorang pahlawan nasional keturunan Indo-Eropa, Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi).
Jiwa patriotismenya sebagai sang inspirator revolusi melanjutkan semangat seorang pengkritik kolonialisme yang terkenal, Edward Douwes Dekker (Multatuli), pengarang buku Max Havelaar, yang memiliki pertalian keluarga dengan Ernest sebagai adik dari kakeknya.
Meski di tubuh Ernest mengalir darah campuran multietnis dan ras (Belanda, Perancis, Jerman dan Jawa) dan bukan penduduk Indonesia tulen, namun kecintaannya kepada Tanah Air Indonesia begitu bergelora, melebihi sebagian kalangan pribumi sendiri, sehingga P.J.A. Idenburg melukiskannya sebagai “orang Jawa yang anti-Belanda.”
Dihadapkan pada aneka bentuk diskriminasi kolonial Belanda, baik terhadap golongan pribumi maupun Indo, ia mengobarkan semangat kemajuan dan persatuan baik bagi kaum pribumi maupun keturunan. Pada awal 1900-an, rumah Ernest yang terletak di dekat STOVIA menjadi tempat berkumpul para perintis gerakan kebangkitan nasional Indonesia, seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetomo, untuk belajar dan berdiskusi. Ia merupakan salah seorang yang membantu kelahiran Budi Utomo, bahkan menghadiri kongres pertamanya di Yogyakarta.
Selanjutnya, Ernest tampil sebagai peletak dasar nasionalisme Indonesia atas dasar kesamaan tumpah darah (bukan atas dasar kesamaan etnis-agama), yang dicoba diperjuangkannya dengan merintis pendirian partai politik pertama di negeri ini, IP (Indische Partij) pada 1912.
Ernest bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), dikenal sebagai “Tiga Serangkai” yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dengan semangat kebangsaan yang berbasis multikulturalisme.
Sebagai penulis, wartawan, aktivis politik dan pendidik yang lantang menentang kolonialisme, Ernest berulangkali ditangkap, dipenjarakan dan diasingkan di dalam dan luar negeri (Belanda, Suriname). Namun, panggilan Ibu Pertiwi selalu saja membuatnya berjuang mencari jalan untuk pulang ke Tanah Air.
Pembuangan pertama terjadi pada 1913 ke Negeri Belanda, bersama Tjipto dan Soewardi, menyusul penerbitan tulisan Soewardi “Andai Aku Seorang Belanda”, yang mengkritik kolonialisme Belanda. Sekembalinya di Tanah Air pada 1918, ia ditangkap lagi oleh Belanda pada 1919 karena dianggap memprovokasi gerakan buruh di perkebunan Polanharjo, Klaten.
Selepas penangkapan, ia hijrah dari Semarang ke Sukabumi, lantas menetap di Bandung sejak 1922 untuk berperan sebagai pendidik yang mengobarkan semangat patriotisme, dengan mendirikan Ksatrian Instituut, yang menjadi mitra sehaluan dengan Perguruan Taman Siswa (pimpinan Soewardi/Ki Hadjar Dewantara).
Tahun 1941, ia kembali ditangkap dengan tuduhan menjadi kaki tangan Jepang, lantas dipenjarakan di Ngawi, Magelang, dan Madiun. Pada 1942, ia dibuang kembali ke Suriname melalui Belanda. Kondisi kehidupan di kamp sangat memprihatinkan, sampai-sampai Ernest yang waktu itu sudah memasuki usia 60-an, sempat kehilangan kemampuan melihat.
Ketika Perang Dunia berakhir, para interniran (buangan) di Suriname tidak segera dibebaskan. Baru menjelang pertengahan 1946, sejumlah orang buangan, termasuk Ernest, diterbangkan ke Amsterdam, pada 19 Juli. Namun, dengan menempuh jalan berliku, pada 6 Desember 1946, ia berhasil melarikan diri ke Indonesia, dengan menggunakan dokumen atas nama Jopie Radjiman dan menumpang kapal SS Welterveden. Setiba di Tanjung Priok, ia melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, dan langsung menemui Bung Karno di Istana Negara pada 4 Januari 1947.
Di Istana saat itu, hadir sejumlah tokoh yang menantinya: Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Radjiman Wediodiningrat dan Arudji Kartawinata. Soekarno menyambut kedatangannya dengan pelukan erat dan sapaan hangat, “Selamat datang, Nest.” Ernest menjawab dengan berseloroh, “Saya gembira bahwa pada hari tua saya dapat kembali di antara saudara-saudara untuk menawarkan jasa saya kepada Republik, kendati sebagai prajurit biasa. Sebab saya adalah seorang penembak jitu.” Bung Karno lantas memberinya nama “Danudirdja Setiabudhi”. Danudirdja berarti banteng yang kuat, sedangkan Setiabudhi berarti jiwa kuat yang setia.
Pemerintah mengangkatnya sebagai menteri negara tanpa portofolio dalam Kabinet Sjahrir III, merangkap Pengurus Perpustakaan Negara, lalu sekretaris politik, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Soekarno juga mengangkatnya sebagai penasihat pribadi. Setelah terjadi Agresi Militer Belanda, Ernest dilibatkan dalam pertemuan dengan delegasi Belanda yang datang dari Jakarta ke Yogyakarta. Setelah Agresi Belanda I, pada 21 Juli 1947, PBB meminta Indonesia dan Belanda melakukan perundingan.
PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Frank Porter Graham (AS), Richard C. Kirby (Australia) dan Paul van Zealand (Belgia). Komisi Tiga Negara ini memfasilitasi perundingan Indonesia dengan Belanda di atas Kapal USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin Amir Sjarifuddin Harahap dan Ernest Douwes Dekker, sedangkan Belanda diwakili oleh perwira KNIL, Kol. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Perundingan di atas kapal itu menyepakati penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada 17 Januari 1948.
Pada 21 Desember 1948, Belanda kembali menciduk Ernest dalam Agresi Belanda II.
Setelah diinterogasi, ia dikirim ke Jakarta untuk diinterogasi kembali. Namun, tak lama kemudian Ernest dibebaskan berhubung kondisi fisiknya yang payah dan setelah berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik. Ia dibawa ke Bandung atas permintaannya dan meninggal di kota yang sama pada 28 Agustus 1950. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung; Nama Setiabudi diabadikan sebagai nama jalan dan kawasan di Bandung dan Jakarta, sebagai penghormatan atas jasa-jasanya sebagai kusuma bangsa (Tempo, 2012).
(Yudi Latif, Makrifat Pagi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid