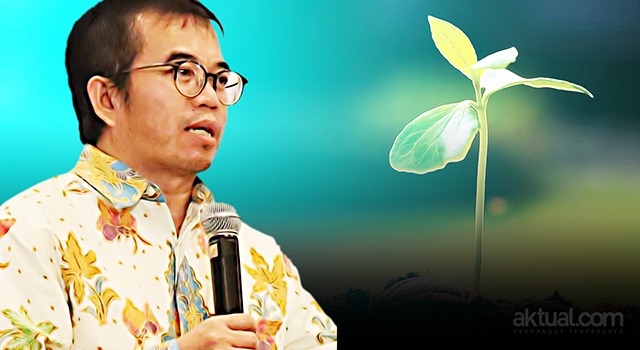Jakarta, Aktual.com – Dari mana kebangkitan nasional harus dimulai? Dari kesadaran pentingnya keutamaan budi; budi utama. Belajar pada sejarah, awal abad ke-20, kesadaran itu bukan hanya tercermin dari kelahiran Budi Utomo, tetapi juga organisasi sejaman seperti Jamiat Khair (perkumpulan kebajikan budi), dan juga Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia: sakti, budi, bakti). Singkat kata, budi pekerti (karakter) adalah tumpuan utama kebangkitan dan kemajuan.
Presiden Indonesia pertama, Soekarno, mengisahkan pengalaman yang menggugah ketika beliau diwisuda di Technische Hoogeschool (Sekarang Institut Teknologi Bandung). Ketika Rektor menyerahkankan ijazah insinyur kepada Bung Karno, secara mengejutkan ia berkata, “Ir. Soekarno, ijazah ini suatu saat dapat robek dan hancur menjadi abu. Dia tidak abadi. Ingatlah, bahwa satu-satunya hal yang abadi adalah karakter dari seseorang.” Atas ucapan tersebut Bung Karno mengatakan, “Kenangan terhadap karakter itu akan tetap hidup, sekalipun dia mati. Aku tak pernah melupakan kata-kata ini.”
Karakter adalah lukisan sang jiwa; ia adalah cetakan dasar kepribadian seseorang/sekelompok orang, yang terkait dengan kualitas-kualitas moral, ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya, sebagai hasil dari suatu proses pembudayaan dan pelaziman (habitus).
Sedemikian pentingnya nilai karakter bagi eksitensi seseorang/sekelompok orang, sehingga dalam peribahasa Inggris dikatakan, “When wealth is lost, nothing is lost; when healt is lost, something is lost; when character is lost, everything is lost.” Apapun yang dimiliki seseorang, kepintaran, keturunan, keelokan, kekuasaan menjadi tak bernilai jika seseorang tak bisa lagi dipercaya dan tak memiliki keteguhan sebagai ekspresi dari keburukan karakter.
Karakter bukan saja menentukan eksistensi dan kemajuan seseorang, melaikan juga eksistensi dan kemajuan sekelompok orang, seperti sebuah bangsa. Ibarat individu, pada hakekatnya setiap bangsa memiliki karakternya tersendiri yang tumbuh dari pengalaman bersama. Pengertian “bangsa” (nation) yang terkenal dari Otto Bauer, menyatakan bahwa, “Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman.”
Tentang pentingnya karakter bagi suatu bangsa, Bung Karno sering mengajukan pertanyaan yang ia pinjam sejarawan Inggris, H.G. Wells, “Apa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa?” Lantas ia jawab sendiri, bahwa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa bukanlah seberapa luas wilayahnya dan sebera banyak penduduknya, melainkan tergantung pada kekuatan tekad, sebagai pancaran karakternya.
Bagi bangsa Indonesia, karakter kebangsaan itu berjejak pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar, isi hidup dan arah hidup bagi perkembangan bangsa.
Tantangannya adalah bagaimana mencetak nilai-nilai ideal Pancasila itu menjadi karakter kebangsaan, melalui pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan, dan kesungguhan komitmen untuk mengamalkanya dalam segala lapis dan bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Untuk itu, diperlukan pendekatan sosialiasi Pancasila secara lebih kreatif dan holistik, meliputi dimensi kognitif, afektif dan konatif, yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam Amanat Proklamasi, 17 agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa memiliki kekuatan karakter yang dibangun atas dasar kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa. ”Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus mempunyai levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi-hidup dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang tidak mempunyai levensdiepte samasekali. Ia adalah bangsa penggemar emas-sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat,–tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong-mlompong di bagian dalamnya.”
(Yudi Latif, Makrifat Pagi)