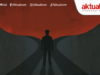Oleh: Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP*
SULIT menampik kenyataan bahwa banyak advokat di Indonesia hari ini berjuang di medan yang nyaris selalu buntu. Di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung dalam rumpun peradilan umum; di Pengadilan Tata Usaha Negara; di Pengadilan Agama; di Pengadilan Militer; dan bahkan di Pengadilan Pajak yang secara struktur masih dalam transisi dari “dua atap” (Mahkamah Agung–Kementerian Keuangan) menuju “satu atap” di Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026.
Di atas kertas, semua lembaga ini adalah penjaga keadilan. Di lapangan, terlalu sering advokat berhadapan dengan putusan yang tercium lebih sebagai kompromi kekuasaan daripada penegakan hukum. Skandal korupsi di Mahkamah Agung dengan figur seperti Zarof Ricar, mantan pejabat MA yang akhirnya dihukum 18 tahun penjara dan dirampas uang sekitar Rp915 miliar serta 51 kg emas, hanya puncak gunung es yang kebetulan terbongkar ke publik.
Di tengah realitas itu, teknologi informasi yang digembar-gemborkan di lingkungan MA, seperti e-court, e-litigation, aneka dashboard dan sistem informasi, sering terasa hanya sebagai “make up digital” di atas wajah lama peradilan yang masih keropos. Sistemnya tampak modern, tapi kultur hukumnya tetap sama: hakim yang sibuk menjadi corong undang-undang, bukan penegak hukum dan keadilan. Keadilan dikorbankan atas nama kepatuhan formal pada bunyi pasal, seolah-olah teks undang-undang selalu suci dan kebal terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Di titik buntu seperti inilah banyak advokat mulai menemukan pola: putusan-putusan yang seragam, alur logika yang berulang, dan argumentasi hakim yang berhenti pada “karena bunyi undang-undang seperti ini”. Ketika ruang tafsir di peradilan biasa tertutup oleh cara pandang “corong undang-undang”, advokat terpaksa mencari pintu lain: Mahkamah Konstitusi.
Advokat yang kelelahan dihantam putusan formalistik di semua jenjang peradilan mulai melirik Mahkamah Konstitusi sebagai medan perjuangan baru. Di sana, mereka tidak lagi sekadar memperjuangkan “si A melawan si B”, melainkan menggugat makna norma: frasa, pasal, atau ayat yang menjadi sumber lahirnya ketidakadilan di peradilan biasa.
Di Mahkamah Konstitusi, advokat mengajukan uji materiil:
mereka bertanya, “Apakah pasal ini, dalam bunyi dan penerapannya, masih selaras dengan UUD 1945?”
Di forum ini, pola berulang dari putusan peradilan biasa, hakim yang menyembunyikan diri di balik teks undang-undang, ditarik ke tingkat yang lebih tinggi: konstitusinya sendiri diuji.
Tidak sedikit advokat atau pemohon yang kemudian menang. Sejumlah norma dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sebagian lain dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dimaknai ulang, atau dipersempit penerapannya. Putusan-putusan ini mengubah lanskap hukum, kadang secara sangat nyata: dari hukum pajak, pidana, tata usaha negara, sampai hak-hak konstitusional warga.
Namun di sinilah ironi sekaligus problem barunya muncul:
sebagian advokat mulai menganggap putusan MK itu milik pribadinya.
Mereka bicara di media, di forum, bahkan di kalangan profesi seolah-olah: “Ini kemenangan saya.” “Ini putusan saya.”
Lupa satu hal mendasar: putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan putusan privat, ia bersifat erga omnes, mengikat seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pemohon.
Secara logika hukum, advokat yang mengajukan uji materiil di MK sedang memainkan peran yang berbeda dari advokat yang membela klien di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Pajak. Di pengadilan biasa, konstruksinya jelas: ada penggugat–tergugat, ada terdakwa–penuntut umum, ada sengketa yang hasil akhirnya memang langsung menyentuh klien tertentu. Di sini, wajar jika advokat berkata, “Saya memenangkan perkara untuk klien saya.” Karena memang orbitnya privat.
Tetapi di Mahkamah Konstitusi, panggungnya lain. Permohonan uji materiil terhadap undang-undang, meski lahir dari kasus konkret yang dialami pemohon, pada hakikatnya menyentuh nasib semua orang yang berada di bawah jangkauan norma itu. Putusan MK yang mengubah, menafsirkan ulang, atau membatalkan suatu norma berlaku untuk seluruh warga, bukan hanya untuk pemohon yang datang lebih dulu. Undang-undang tidak lagi boleh dibaca dengan cara lama, bukan hanya terhadap satu klien, tetapi terhadap seluruh bangsa.
Di titik ini, ketika advokat mengklaim: “Ini putusan saya, hasil jerih payah saya, jangan seenaknya dipakai orang lain,” maka di situlah kesesatan logika itu berdiri tegak.
Ia lupa bahwa ketika melangkah ke MK, ia sebenarnya telah naik kelas: dari sekadar pembela klien menjadi aktor konstitusional. Ia tidak lagi hanya bermain di arena kepentingan privat, tetapi sudah menyentuh ruang kepentingan publik, bahkan kepentingan negara dalam arti yang lebih luas.
Jika ingin menikmati putusan sebagai “hak milik pribadi”, seharusnya tetap bermain di pengadilan umum, TUN, agama, militer, atau pajak. Di sana, struktur sengketanya memang dirancang untuk hasil yang berorientasi pada pihak-pihak tertentu. Tapi begitu melangkah ke Mahkamah Konstitusi, medan itu bergeser: yang dipertaruhkan adalah makna norma bagi seluruh rakyat.
Di tengah mentalitas sebagian advokat yang terjebak merasa “memiliki” putusan MK, muncul contoh yang menarik dari dunia perpajakan. Seorang kuasa hukum pajak bernama Fungsiawan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, terkait larangan perekaman audio visual dalam setiap pertemuan antara wajib pajak dan fiskus.
Inti persoalannya sederhana tapi sangat penting: DJP selama ini menafsirkan Pasal 34 UU KUP sebagai dasar melarang wajib pajak atau kuasanya merekam pertemuan dengan petugas pajak. Padahal, secara tekstual, norma itu justru melarang pejabat pajak membocorkan rahasia wajib pajak, bukan melarang wajib pajak mendokumentasikan sendiri pertemuan resmi yang menyangkut hak dan kewajibannya. Fungsiawan menggambarkan bagaimana rekaman yang seharusnya wajib dilakukan secara internal oleh fiskus justru sering tidak ada, sementara larangan merekam justru diberlakukan kepada wajib pajak.
Dengan uji materiil ini, ia tidak sekadar membela satu klien dalam satu sengketa pajak. Ia sedang membuka jalan agar setiap wajib pajak kelak bisa merekam proses pertemuan dengan fiskus sebagai bagian dari hak atas transparansi dan alat bukti yang fair. Kalau permohonannya dikabulkan, dampaknya tidak berhenti di dirinya: semua warga negara yang berhadapan dengan pejabat pajak akan ikut merasakan perubahan itu.
Dan yang menarik, cara dia memposisikan diri bukan sebagai pemohon yang berkata, “Kalau saya menang, ini hak saya,” melainkan sebagai perjuangan untuk seluruh wajib pajak yang sering berada di posisi lemah, berhadapan dengan tafsir sepihak pejabat pajak yang berlindung di balik bunyi pasal.
Inilah yang seharusnya menjadi standar moral advokat di Mahkamah Konstitusi: ketika menguji undang-undang, mereka sedang bertindak sebagai warga yang berjiwa negarawan, bukan hanya sebagai pedagang jasa hukum.
Karena itu, di tengah krisis kepercayaan terhadap peradilan, korupsi di Mahkamah Agung, putusan-putusan yang terindikasi dipengaruhi oknum, dan digitalisasi yang lebih mirip kamuflase daripada reformasi, Mahkamah Konstitusi sering dipandang sebagai salah satu sisa ruang harapan. Tetapi ruang ini hanya akan benar-benar menjadi berkah bagi rakyat jika para advokat yang memasukinya siap melepaskan ego profesi dan logika “milik pribadi”.
Putusan MK adalah milik konstitusi, dan melalui konstitusi, ia menjadi milik seluruh rakyat. Advokat boleh tercatat sebagai pemohon, boleh berbangga sebagai penggagas argumen, boleh menuliskan namanya dalam sejarah perkara; tetapi hak menikmati putusan itu tidak boleh dimonopoli. Justru ukuran keberhasilan moral seorang advokat di Mahkamah Konstitusi bukan hanya saat permohonannya dikabulkan, melainkan ketika ia rela melihat:
- putusan itu dipakai orang yang tidak ia kenal,
- dimanfaatkan oleh wajib pajak kecil di kabupaten yang jauh,
- dipegang oleh warga yang selama ini tidak punya akses pengacara sekalipun,
dan ia tetap bisa berkata dalam hati: “Memang sejak awal, ini bukan untuk saya sendiri. Ini untuk kita semua.”
Di tengah krisis peradilan, kita butuh lebih banyak advokat yang mengerti perbedaan itu, yang paham bahwa menang di MK berarti mengikat bangsa, bukan mengunci hak atas putusan untuk dirinya sendiri. Kalau Mahkamah Agung sedang diuji oleh skandal dan rapuhnya integritas, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi tempat di mana jiwa kenegarawanan para advokat diuji.
Dan ujian pertama mereka sederhana, beranikah mereka berhenti menganggap putusan MK sebagai milik pribadi?
*Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia,
Anggota Majelis Tinggi Partai X,
Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi